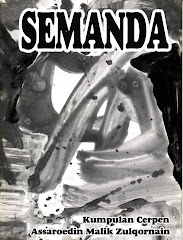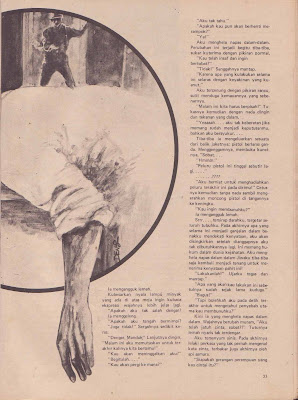










Sumber: MAJALAH DETEKTIF & ROMANTIKA (D&R)






















SUMBER : MAJALAH HUMOR




 SUMBER DARI MAJALAH SENANG
SUMBER DARI MAJALAH SENANG

 SUMBER DARI MAJALAH NOVA
SUMBER DARI MAJALAH NOVA


 SUMBER DARI MAJALAH KHARISMA-BANDUNG
SUMBER DARI MAJALAH KHARISMA-BANDUNG
 SUMBER DARI MAJALAH HARMONIS
SUMBER DARI MAJALAH HARMONIS





























Dari Suara Karya Minggu (SKM), Jakarta
TEKS CERITA PENDEK
SEMANDA
Cerpen asaroeddin malik zulqornain
Sudah tiga-pagi ini Batin Unyin bertandang ke kandang ayam Tamong Ubai sambil menggendong “si-Nyongbai” : ayam betina miliknya. Tak jadi soal apakah si pemilik ayam jago-bangkok itu sedang ada atau tidak dirumah panggungnya. Toh, pada pagi pertama tandangnya tempo hari, Tamong Ubai sudah kasih izin padanya untuk mengantarkan Nyongbay bersebadan dengan si lapah cukut di kandangnya. Dia pun tak ambil peduli dengan sorot mata suami-suami lain didesa Pekon Ampai yang kebetulan berpapasan dengannya. Sungguhpun kiprahnya ini bertentangan dengan kenyataan. Suami-suami lain pikirnya, boleh-boleh saja disetiap pagi manis bangkit turun dari
rumah panggung masing-masing dengan menggendong cangkul, bercaping, dan bergumul lumpur di sawahnya tapi bagi Batin Unyin adalah soal lain.
Pun bukan lantaran dia tak punya sawah ada kira-kira sepuluh bidang, kebun lima bidang, kolam ikan sebidang. Tapi buat apa dia kerja keras? Begitu selalu pikirnya. Toh semua itu milik putrinya: seorang tandok:anak perempuan yang berkewajiban untuk merawat ayah bundanya, tidak boleh keluar dari rumah budel itu sekalipun telah menikah dan suaminya harus berstatus semanda: (turut istri). Alhasil Batin Unyin cuma berkewajiban mencangkuli bininya. Soal anak harta dan keluarga adalah tanggung jawab istrinya.
Percuma pula ia capek-capek kerja begitu selalu pikirnya. Jika hasilnya tak bisa dikuasainya secara penuh. Bapak mertua, ipar-ipar pasti akan mengingatkan status dirinya yang diambil jika Batin Unyin berbuat macam-macam!
Nama aslinya: Rustam. Batin Unyin adalah adok yang diberikan pemuka Adat desa pekon Ampai ketika dia resmi diambil mantu oleh Tumengung Karai, jadi suami dari Nilam yang adoknya: Ratu Kemala Bumi. Batin Unyin pendatang dari tanah seberang di Pekon Ampai itu dia mungkin cuma di temani si Nyongbay.
Batin Unyin memang punya tiga orang keturunan. Dua lelaki satu perempuan. Tapi sejak orok dididik untuk ikut ibunya.
Batin Unyin tak ubahnya seperti nasib si lapah-cukut milik Batin Ubai. Boleh-boleh saja si lapah cukut menyimpan bibitnya di rahim si Nyongbay tapi soal telur, soal anak, soal masa depan anak-anaknya adalah sepenuhnya milik si Nyongbay. Memang Batin Uyin dan lapah cukut itu agaknya senasib.
Sudah tiga pagi ini Batin Unyin dengan sabar menunggu dimuka kandang. Sorot matanya yang selalu kuyu seketika berbinar jika saksikan lagak bandot tua; lapah cukut menyebadani si babon montok Nyongbay miliknya. Batin Unyin tak hirau pokok sedih si lapah cukut ketika kedua tangannya menjemput Nyongbay dari sisinya. Toh Nyongbay itu miliknya seratus persen, begitu pikirnya sambil berjalan pulang.
2
Kiprahnya ini tentu saja mengundang ketidaksenangan orang rumah.
“Abang tidak ke sawah?” sindir istrinya.
Batin Unyin pura-pura tuli, sibuk melinting rokok nipahnya.
“kan musim tanam sudah tiba, bang?”
Yang ditegur malahasik menikmati kreteknya.
“Abang kok diam saja? Marah ya? Gara-gara tak diizinkan ayah untuk ikut pulang mudik lebaran nanti?”
Batin Unyin menggeratakkan gerahamnya. “Saya sih mau saja, ayah pun mengizinkan, yang tak dizinkannya apabila kepergian itu dengan membawa anak-anak dan perhiasan” kembali istrinya mereplay kasus yang terjadi sebulan lalu, “Bicara dong….?” Sergah istrinya mulai kesal.
“Nah, nah…………….itulah soalnya” cetus Batin Unyin seperti menemukan kilah yang tepat untuk mulai bicara. “Itulah sebabnya sejak tiga pagi ini saya selalu menggendong Nyongbay kekandang si lapah cukut milik si Ubai itu”
Istrinya melongo………
“Nyongbay adalah segala-galanya bagiku kini dan dengan bantuan benih unggul dari si lapah cukut aku yakin bakal berharga di matamu, dimata mertuaku, dimata ipar-ipar dan dimata orang kampung ini.”
“Engkau menempuh jalan yang keliru bang?!”
“Aku sudah bosan jadi bedua kalian maka itu kutempuh jalan yang kau anggap keliru ini” cetusnya bersemangat. “Tapi bagiku inilah jalan tol yang tepat untuk mengantarkan aku pulang kampung lebaran tahun depan dengan sejuta kebanggan…..dengan berterlurnya si Nyongbay kelak, itulah awal dari suatu jalan panjang menggapai kebebasan!Nyongbay kelak akan menetaskan cikal bakal jago bangkok blasteran yang kampium di gelanggang persabungan manapun juga. Aku dengan menggendong ayam jagoku kelak akan melanglang kemancanegara untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Dan dengan uang hasil kemenangan itu akan kunikmati setiap gadis yang kucintai di setiap persinggahan petualanganku kelak. Akan kusemai bibit unggul seorang Batin Unyin ke rahim-rahim mereka. Pada akhirnya aku akan memiliki keturunan ditiap bangsa. Tidak seperti sekarang ini hanya memiliki tiga keturunan dari satu bibit di satu desa dan semanda pula.” Kalimat akhir ini hanya sampai ditenggorokannya, bergaung balik menghantam dadanya, membuat napasnya sesak dan pandangannya nanar. Sementara istrinya sudah bergulir ke ruang belakang jauh sebelum igau dan obsesinya itu selesai diucapkannya.
3
Batin Unyin menghabiskan seluruh waktunya dari pagi sampai petang hanya untuk mempersiapkan cikal bakal dewa penyelamat kesemandaannya. Dirawatnya si Nyongbay dengan telaten. Dibuatnya sebuah kandang yang bagus. Dipilihnya makanan yang bergizi tinggi dinantinya saat Nyongbay berkotek bertelur mengeram dan menetaskan telurnya…sambil tak lupa rajin merapal mantera-mantera dari gunung Pesawaran. Sebab dari sanalah Nyongbay berasal, diambil dari seorang pertapa sakti: Datuk Tuan Guntur Dunia. Ditebus dengan uang tiga puluh ribu perak, uang kaget
(yang diperoleh Batin Unyin waktu pasang nomor SDSB 2374 padahal nomor yang keluar 9374……ya Cuma salah kepala, dia Cuma dapat untuk pasangan Rp500 untuk yang dua angka). Padahal coba kalau pasangnya 9374 wuuaaaah…….dia pasti bakal menggondol duit puluhan juta perak, sebab dia pasang SDSB sampai 25 ribu perak, uang hasil penjualan beberapa ekor ayam peliharaannya.
Batin Unyin begitu yakinnya bahwa lewat pantat Nyongbay dia akan memperoleh kehormatan untuk jadi orang terhormat. Dan tak terperikan kegembiraannya tatkala pada pagi ketiga belas, Nyongbay mulai berkotek….
Disiapkannya tilam dari serat bambu yang paling halus untuk persemayaman telur-telur kebebasan itu. Namun dia tidak merasa perlu untuk menyampaikan berita bagus ini kepada pemilik si lapah cukut. Toh pikirnya yang bertelur ayamnya sendiri? Toh si lapah cukut sudah diservis tubuh montok Nyongbay? Jadi perlu apa repot-repot haturkan terimakasih bahkan persoalan bisa tambah runyam kalau Tamong Ubai sampai tahu. Bagaimanapun dia akan menolak metah-mentah kalau sampai si Ubai minta bagi hasil. Alhasil Batin Unyin merahasiakan warta bertelurnya si Nyongbay ini bukan saja kepada Tamong Ubai tapi juga kepada seluruh anggota keluarganya.
Dasar anak-anak yang masih polos ketiga putranya : Pipin, Pitut, dan Pido yang terbiasa makan telur telur setiap pagi dan kebiasaan itu terhenti akibat bapaknya menjual semua ayam miliknya, kini keinginan itu berkobar-kobar dalam lidah mereka untuk makan telur ayam rebus.
Mereka maklum cara minta secara baik-baik pasti tak bakal diberi oleh bapaknya. Menunggu saat yang tepat untuk mengambil telur-telur dari sangkarnya adalah jalan paling tepat. Jalan itu terbuka lebar pagi ketika diketahui oleh mereka bahwa bapaknya sedang buang air besar di sungai belakang rumah. Ketiganya tanpa dikomando langsung menyerbu sangkar. Masing-masing seorang satu, meyisakan tiga butir lagi disangkarnya.
“Wow………….bapak kalian pasti akan marah besar” pekik ibuya ketika melihat ketiga anaknya menyodorkan telur untuk direbus, “hayo kembalikan cepat! Jangan sampai bapak kalian tahu! Itu telur jimat, telur ajaib kata bapakmu, ayo…….!”
4
Ketiga anak itu membatalkan maksudnya mengembalikan ketiga telur itu ketempatnya semula ketika dilihatnya bapak mereka sudah ada dimuka sangkar. Mendelik bola mata Batin Unyin melihat telur-telur harapannya tinggal tiga butir. “pipin, Pitut, Pido….!” Pekiknya mengguntur.
Ketiga anaknya datang tanpa telur ditangan dan ketiganya kompak untuk tidak mengaku bahkan ketiganya mengancam akan mengadu kepada kakek mereka kalau sampai Batin Unyin menghajar darah dagingnya sendiri………..
Batin Unyin menghadapi buah simalakama. Batin Unyin pada akhirnya menyadari jika dirinya tak beda dengan nasib si lapah cukut, impian muluknya kandas dibanting oleh perilakunya sendiri yang salah kaprah. (Gedongpakuwon ’91)
MANDIRI
Cerpen Asaroeddin Malik Zulqornain
Jika ditelapak kaki Emak ada Surga mungkin ditelapak kaki Bapak ada Neraka. Itulah sebabnya kaki bapak acapkali melayang ke pantatku bila sepak terjangku dianggapnya terlampau badung. Untung ini cerita seperlima abad silam-nostalgia masa bercelana kodok – Sebab sekarang aku sudah besar, konon kata pejabat sudah jadi pemuda harapan bangsa. Tapi lain lagi pendapat Mas Tarto, karibku. Dia lebih suka menjuluki aku pemuda harapan pemudi!
Kembali kepada Bapak. Sekalipun Bapak sering menendang pantatku, aku tak sakit hati apalagi dendam padanya. Juga tidak kecewa walau bapak tak mampu menyiapkan jatah bulanan lebih dari dua ratus ribu rupiah yang dikirimkannya via pos wesel guna mengongkosi biaya kuliahku di rantau.
Malam baru saja lepas pukul dua puluh dua. Kota tenggelam dalam hujan. Ini adalah waktu yang baik buat tidur lebih nyenyak dengan menarik selimut tinggi-tinggi. Hal ini berlaku buat penghuni rumah gedung di jantung kota yang got-gotnya tak pernah mampet. Lain soal dengan penghuni sepanjang tepian kali, justru inilah saat buat mewaspadai debit air sungai jika tak ingin rumah beserta isinya digerus luapan air.
Meski tempat kost ku amat jauh dari kemungkinan diembat banjir, aku tidak dapat seenaknya menarik selimut. Bukan karena tentamen, bokek, putus cinta apalagi karena her, tapi semata-mata akibat isi surat Bapak yang kuterima siang tadi. Alhasil malam ini pikiranku kalut, murung memikirkan nasib kelarga Bapak di kampung.
“………………tabahkanlah hatimu, Nak. Teruskanlah kuliahmu,” begitu bunyi kalimat awal surat Bapak. “Biarpun tanaman padi kita tahun ini gagal total digerus banjir dan Bapak terjerat tunggakan kredit Bimas tapi bukan alasan untuk menyuruh kamu berhenti kuliah. Hal ini tidak perlu terjadi. Cukup Bapak saja yang tiap hari berkubang lumpur. Dipundakmulah kelak tergantung hari depan keluarga kita…….
Duh, kasihan Bapak sudah menjelang seperempat abad umurku habis terpakai hanya untuk makan ilmu. Menghabiskan bagian terbesar penghasilan sawah ladang Bapak. Aku memang tumpuan harapan keluaga . Bapak amat mendambakan putra sulungnya bisa “jadi orang”. Tugas ini terlampau berat. Gelar kesarjanaan yang kelak ku genggam bukanlah tiket untuk menjamin hari depan yang gemilang.
2
Yang membuat aku malam ini tenggelam dalam murung adalah munculnya arus balik kesadaranku, bahwa sampai detik ini aku masih menetek pada Bapak. Kedua tanganku tidak pernah berusaha mencari rezeki baik halal apalagi haram. Belum pernah sesenpun uang masuk ke kantongku yang merupakan keringatku sendiri. Selama ini aku tahunya hanya terima-ada. Tiap awal bulan yang kutunggu cuma sepotong wesel dari Bapak.
Dipuncak rasa sesal, tiba-tiba mencuat pikiran untuk memulai mengayunkan langkah terobosan hidup mandiri. Bukankah tak ada istilah telat untuk belajar mengetahui bagaimana susahnya cari duit? Atau haruskah kukorbankan kuliahku demi meringankan beban Bapak? Ah itu sama saja dengan menyuruh Bapak menggali lobang kuburnya lebih cepat. Ya bagaimana pun aku harus memulainya. Tapi usahaapa? Ah, pokoknya apa sajalah yang pentinga halal.
Berpikir sampai disini jiwaku sedikit lega, dan mataku baru mau terpejam. Esoknya kuputuskan untuk bolos mata kuliah Antropologi Budaya. Setelah menguangkan wesel di kantor pos langkahku dengan mantap kuarahkan ke alamat mas Tarto, karibku yang biasa mangkal di pojok pertokoan jalan Sibolga, menggelar dagangannya berupa koran dan majalah. Setelah berbasa-basi langsung kusampaikan maksudku.
“Apa? Kamu mau jual koran?” tanyanya membelalak. Aku mengangguk mantap. Ia menatapku aneh. “Hmm………………..tentu anda Cuma bergurau kan?
“Tidak, Mas. Saya serius”
“Masak mahasiswa jualan Koran? gengsi dong sama status, apa nanti kata orang?”
“Persetan dengan status, dengan kata orang, toh urusan hidup seseorang tak bakal ada yang menggubrisnya selain dirinya sendiri. Paling banter mereka cuma nuding dan mencibir. Soal itu gampang mas, cuekin aja.”
“Cuek sih cuek dik,” sambutnya. “Tapi perlu diingat juga siapa dirimu,. Kan kamu punya teman kuliah, pacar, dosen. Laaaaa………..apa mereka bisa kamu cuekin? Bagaimana kalau gara-gara koran, kamu lantas dikucilkan dari pergaulan, dan pacarmu memutuskan hubungan diplomatiknya? Nah, kamu sendiri nanti yang rugi?”
“Mas keberatan menolong saya?”
Laki-laki berbadan makmur dan berkaca mata minus itu terdiam.
3
Segera kututurkan semua kemelut yang sedang kuhadapi. Tentang panen yang gagal, tunggakan kredit Bimas yang macet, ongkos kuliah yang selalu naik-naik kepuncak gunung dan tentang tekadku untuk mulai belajar mencari duit yang halal.
Agaknya mas Tarto terenyuh dan mulai memaklumi sikonku. “Apakah niat kamu sudah bulat, Dik?”
“Aku lekas mengangguk “seperti bola bekel Mas”.
Mas Tarto tersenyum dan menjabat tanganku erat-erat, orang macam kamu memang perlu diplonco sebagai penjual koran kaki lima biar kamu tahu rasa, bagaimana susahnya cari duit yang halal itu. Lamaranmu saya terima; tak perlu pakai uang pelicin dan koneksi. Tapi berhubug kamu sahabat saya tentu saja kamu tak bakal saya suruh jualan koran keliling pasar; kamu cukup dengan menggantikan kedudukan saya. Setiap hari kamu kerja mulai pukul lima belas sampai pukul dua puluh dua malam. Sanggup?”
Seketika kusambar tangannya kucium dengan penuh rasa teimakasih.
“Menghidupi hidup ini memang tak cukup hanya mengandalkan kepintaran, hidup juga membutuhkan tuah”, katanya serius. “Nah moga-moga lewat jualan koran ini kepintaranmu jadi bertuah sebab langsung diproses dalam pergumulan hidup dilapangan.”
“Makasih Mas,” sambutku dengan hati berbunga-bunga. Dengan langkah bagai serdadu menang perang, aku pamit padanya untuk kembali sore nanti. Kudatangi kantor pos kutulis surat buat Bapak di kampung.
“Bapak, wesel dan surat Bapak sudah ananda terima. Soal ongkos kuliah bulan depan kirim saja separuh dari jumlah yang biasa. Dan soal ongkos hidup ananda dirantau mulai bulan ini Bapak tak perlu lagi merisaukannya. Anakmu sekarang sudah bisa cari duit sendiri…….”
Putra Sulungmu,
Togop
Sebulan kemudian ketika magangku kian mapan sebagai penjaja koran dipojok pertokoan, aku memutuskan untuk berhenti menetek pada Bapak. Perkembangan lainnya beberapa teman kuliaku sudah banyak yang tahu profesiku. Rata-rata mereka cuma menggeleng dan mencibir, tapi kucuekin saja.
Terakhir giliran pacarku mengetahui profesiku. Dia menginterogasi aku. dengan enteng kujawab. “Iya”. Pacarku kaget untung tidak shock. Soalnya dia mahasiswi yang anak gedongan jadi mana tahaaaan?!
4
Dugaa mas Tarto ternyata pas betul. Pacarku kasih ultimatum: tetap sebagai kekasihnya atau memilih jualan koran. Jawaban detik itu kusampaikan dengan lantang: “Koran!” pacarku langsung menggelinding ke dalam kamarnya aku pulang dengan dada lapang.
Soal pacar soal gampang. Tapi urusan hidup mandiri adalah soal prinsip dalam upaya mengacu kepada proses pintar yang betuah.
Berkat modal cuek yang positif kini aku berhasil ‘jadi-orang’ dalam arti yang sebenarnya. (Sukamaju, 090106)
DENTING BAHAGIA MALAM TAKBIR
Cerpen Asaroeddin Malik Zulqornain
Ramadhan suci bersijingkat pulang begitu sang-mentari terakhi tergelincir di ufuk barat. Ramadhan suci siap menepi di rembang petang, sesaat lagi akan jatuh dalam pelukan malam fitri.
Saat Buana bergelimang fatamorgana, saat bagi semua umat serentak menguakkan gapura ampunan dengan kedua tangan terencang sambil melantunkan gema takbir dan tahmid memuja kebesaran Al-Chaliq.
Malam takbir, malam dimana bintang-bintang bertahta dalam labirin kalbu, berstanza dalam acuan gema bedug bertalu-talu menyongsong kehadiran Idul Fitri bersama terbitnya sang mentari esok pagi!. Idul Fitri adalah saat bagi setiap insan. kamil tuk saling melebur segala dosa dan khilap; busana kita yang paling purba. Agaknya sudah pasti jika tiap jiwa merasa terpanggil tuk melebur ruhnya dalam ruh kefitrian, dalam ritus jabat tangan yang tulus dan peluk cium. Sebab Idul Fitri adalah kemah tempat segenap insan tuk menanggalkan terompahnya, duduk berkeliling, melepas kesendirian dan sepi sambil mereguk zamzam persaudaraan yang saling asih, asah dan asuh.Semua orang tentukan berbuat demikian, kecuali bagi orang-orang semacam Pamansrun?
Pamansrun-lelaki tua bertongkat akar bahar-penghuni rumah panggung di mulut desa Gedongpakuon, di rembang petang akhir ramadhan ini agaknya lebih senang terbantun luruh dalam jerat ketermanguan, dalam acuan sepi sekeping hati tua yang demikian dahaga direnggut kebersamaan dan peluk cium darah dagingnya.
Impian indah sekeping hati tua menyongsong tibanya Idul Fitri esok pagi, saat segenap darah dagingnya kan datang bersimpuh, saat rumah pangungnya semarak dengan tawaris para cucu, kini tetap tinggal mimpi!. Barangkali tiada kebahagian lain selain malam ini berkumpul dengan anak-cucuk, sekaligus tiada kepedihan yang lebih pedih selain menikmati Idul Fitri seorang diri.
Seusai menunaikan sholat maghrib-setengah jam lalu pamansrun agaknya lebih senang duduk berjuntai diteras rumah pangungnya, engan pergi bertakbir di surau. Dibawah gelimangan sinar pelita minyak yang sesekali mengerlip si cumbu sang bayu, samar terceta gurat-gurat duka di raut wajahnya. Sebab untuk pertama kali dalam hidupnya Pamansrun kan menyongsong Idul Fitri seorang diri!
Sendiri memeluk sepi di malam fitri, satu hal membuatnya termangu dan menangis dalam hati!. Tentu kekecewaannya ini akan sedikit terobati kalau saja istrinya masih setia mendampinginya, saying istrinya telah lebih dahulu pulang kepangkuan-Nya beberapa bulan silam. Sedang ke-empat orang anak perempuannya yang kini telah bersuami dan tinggal di empat kota, agaknya sepakat untuk hanya mewakilkan kehadiran mereka lewat sepucuk kartu lebaran, pos paket dan warta tak bisa pulang mudik!. Hal-hal inilah yang membuat Pamansrun tenggelam dalam denting sendu malam takbir, denting sepi hari tua yang nyaris sempurna.
“Bu..” desisnya tanpa sadar, ”Anak-anak telah mulai melupakan aku setelah kepergianmu, mereka telah mulai melupakan kampung halamannya” keluhnya dengan jiwa remuk redam.
Isi ke-empat surat yang dikirimkan oleh ke-empat orang anaknya itu memang sangat menyakitkan sekaligus menghancurkan impiannya selama ini. Lastrik, putri sulungnya tak bisa pulang mudik karena suaminya sedang ke luar negeri. Lalu Linda berkabar senada dengan alasan baru saja melahirkan anaknya yang nomor dua, putri ketiga Lidia, begitu juga dengan dalih ibu mertuanya sakit keras. Akhirnya si bungsu Leony sepakat dengan ketiga kakaknya, dengan dalih: sedang hamil besar!.
“ Kubesarkan mereka dengan penuh cinta kasih, kurestui mereka berjodoh dengan lelaki kota, namun akhirnya mereka melupakan aku” cetusnya lirih.
“Gusti, memang harus demikiankah nikmat yang mesti kuraih setelah tunai tugasku membesarkan darah daging?. Haruskah anak-perempuan setelah menikah itu ikut suaminya dan melupakan orang tuanya?” Pamansrun tak mampu lagi untuk meredam kekecewaannya.
“Tak ada artinya bagiku kirimkan pos paket, betapa pun mahalnya, yang kudamba adalah kehadiran kalian disini” desisnya dengan hati yang berduka.
Di malam takbir ini Pamansrun terpasung di atas kursi diteras rumah panggungnya, menatap kelu ke luar halaman, dan gelimang gema takbir, dentam bedug bertalu-talu hanya kian menggelamkan dirinya dalam Lumpur kekecewaan. Dan tiba-tiba saja dia untuk pertama kalinya enggan untuk beridul fitri esok pagi. Telinganya merasa sakit mendengar kebesaran malam Fitri!!.
Pamansrun kian tak ambil peduli akan keadaan sekitar, membiarkan jiwanya larut dalam duka, “Kenapa Engkau masih memperkenankan aku ber-idul fitri, Gusti?! Jika semua ini hanya untuk menyengsarakan keberadaanku?!”.
Malam takbir kian memastikan kehadirannya dengan gema azan petanda sholat isya, langit bermandikan bintang gemintang, kidung bintang malam hilang di telan kumandang kebesaran malam takbir, sementara kepekatan di luar kian sempurna, namun Pamansrun pun kian sempurna didera duka. Dia bangkit perlahan, berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya, masuk ke ruang dalam, tidak langsung menghadap tikar sembahyang, namun terus kebelakang rumah, menuruni anak tangga dapur, berjalan dan akhirnya berhenti persis diatas gundukan tanah berbatu nisan, tempat istrinya berbaring abadi.
Dalam gelap yang sempurna ditingkah gaung nyamuk, Pamansrun bersimpuh di atas pusaran istri tercinta…..
Daun pintu rumah pangung itu tetap terbuka lebar, membuat sang bayu kian leluasa mencumbu lampu-lampu minyak yang tergantung di sudut-sudut ruang. Barangkali hanya rumah pangung itu yang enggan ber-takbir, penghuninya lebih senang berada dalam gelap, bermalam takbir di pusara istri tercinta, berjam-jam, waktu mengalir, membuat Pamansrun kian enggan memutuskan silaturahminya.
Selama kepergian Pamansrun, rumah panggung itu didatangi dua-tiga orang tetangga, mengatarkan juadah, namun mereka menemukan rumah tak berpenghuni, pulang dengan hati penuh tanda-tanya. Terakhir yang datang adalah Pak Kyai yang heran Pamansrun tak ikut bertakbir di surau. Pak kiyai sudah berulang-ulang memanggil nama sahabatnya, namun tak ada jawaban. Pamansrun memang tak mendengar semua panggilan, kecuali panggilanNya, untuk itulah dia bersimpuh berjam-jam di pusara istri tercinta. Dimalam takbir itu justru dia punya permintaan aneh: dia amat bahagia jika malaikat menjemput ruh-nya! Ruh-nya enggan dibasuh nur ke-fitrian insani esok pagi?. Satu pinta sekeping hati tua yang letih didera sepi malam takbir!.
Pak kyai menduga tentu Pamansrun sedang tetirah ke rumah tetangga, untuk itu dia bersabar, duduk di kursi kayu di teras rumah sambil terus bertakbir. Pak Kyai maklum jika dia berkewajiban untuk menghibur kalbu sahabatnya yang malam ini pasti di dera sepi akibat ketidakhadiran keluarga besarnya.
Tiba-tiba dari arah kejauhan melesat binaran lampu kendaraan, disusul dengan derunya, terus melaju membuat gelap di sekitar rumah pangung itu bersijingkat, berganti dengan terang-bederang dan akhirnya laju kendaraan itu berhenti di pelataran rumah panggung Pamansrun!.
Pak Kiyai mengerjap-ngerjapkan bola matanya, bangkit bersamaan dengan menghamburnya penumpang dari dalam ke-empat kendaraan itu!
.
“Ayah! Ayaaaah! Kami dating!!” pekik bernada bahagia dari beberapa penumpang kendaraan itu dan langsung menaiki tangga rumah.
Empat pasang keluarga besar itu terperanjat begitu mereka tahu bahwa pria tua yang menyongsong kedatangan mereka adalah Pak Kyai!
“Bersabarlah, dia sedang pergi!” pinta kyai.
“Kemana?” Tanya keluarga besar itu serempak disusul dengan tindak memencar, mencari ayah mertua dan kakek mereka ke segenap penjuru rumah, penjuru kampung, namun tak seorang pun yang terpikirkan untuk menembus gelap di kebun belakang rumah!.
“Ayah menghilang, gara-gara kita mengirim surat itu, pasti!” pekik Lastri kecewa.
“Kita gagal membuat kejutan malam takbir”
Semua merasa berdosa, semua turut sedih, semua merasa kehilangan!.
Sementara Pamansrun yang setengah tuli itu kian tenggelam di rundung duka, enggan bangkit dari simpuhnya……..
Tiba-tiba setelah keluarga besar itu tiba diujung rasa sesal, putri bungsu Leony memekik, “Ayah tidak sedang pergi kemana-mana, dia pasti berada di makam ibu!”
“Ayo kita kesana!”.Pekiknya
Keluarga besar itu berbondong-bondong menuju belakang rumah sambil berteriak, “Ayah…. Ayaaaah……….??!!”.
Pamansrun terjaga dari simpuhnya, mengerjap-ngerjapkan bola matanya, beristighiar, lalu mendung di wajahnya sirna begitu keluarga besarnya mengurung dirinya, Hmm…. kini Denting bahagia malam takbir berkumandang dalam kalbu Pamansrun, “Akhirnya kalian datang juga?!”.
“Ayaaaaah??!!”.
IMPIAN YANG KANDAS
Cerpen Asaroeddin Malik Zulqornain
Pada sisi utara dan selatan bangunan Sekolah Dasar Inpres Lempasing, tempatku mengajar, kini telah berdiri empat pintu bangunan rumah semi permanen. Direnanakan dua pintu diperuntukkan para guru kelas, sisanya masing-masing satu buah untuk Kepala dan Penjaga Sekolah. Karena Ibu Kepala Sekolah lebih kerasan tinggal di rumah pribadiya sedang Pak Penjaga Sekolah sampai kini belum juga di kirimkan pemerintah, otomatis jatah rumah dinas itu jatuh ke tangan Dewan Guru.
Ke-sepuluh orang guru, termasuk aku, sama-sama berhak dan berminat menempati rumah dinas itu. Terlebih lagi lokasi sekolah tempatku mengajar ini masih dalam kawasan kotamadya, walau terletak di ujung barat kota. Disamping tidak perlu mengeluarkan uang kontrak rumah, juga dengan sendirinya menghemat ongkos transport. Resikoya mungkin cuma satu tidak ada alasan membolos.
Mengingat jumlah rumah yang ada tak mencukupi, Ibu Kepala menganjurkan syarat bagi yang akan menempati yakni; sudah berkeluarga, belum memiliki rumah pribadi, berkondite baik dan sudah memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Tentu saja kebijaksanaan Ibu Kepsek itu langsung membuyarkan semangatku yang menggebu-bgebu untuk berlomba memperebutkan hak atas rumah dinas itu. Sebab dari empat syarat itu, dua diantaranya belum dapat kupenuhi. Statusku masih bujangan dan baru lulus ujian pra-jabatan (baru tiga tahun berdinas sebagai Pak Guru). Alhasil sampai detik ini aku masih mondok dirumah Mak Atun satu kilometer dari sekolah.
Ayahku yang dulu seorang guru (sekarang telah pensiun) menghabiskan “cuti-abadi” –nya dikampung sambil menggarap sebidang lahan pertanian, warisan almarhum kakek.
Sampai kini masih segar dalam ingatanku petuah ayah yang disampaikannya menjelang keberangkatanku ke tempat tugas. Kira-kira 200 kilometer dari rumah ayah.
“Karir guru adalah pengabdian,” tutur ayah degngan suara mantap. Oleh karenanya engkau jangan bermimpi bisa memperoleh kekayaan. Dari penghasilanmu kelak yang pas-pasan, engkau hendaknya jangan terlampau banyak berharap. Engkau hanya memiliki dua pilihan dan sangat sulit untuk bisa meraih kedua-duanya. Oleh sebab itu sejak dini bertugas, kau harus mampu memilih salah satu: membangun rumah sederhana atau meyekolahkan anak sampai sarjana. Atau kau ingin mengikuti jejak ayah yang sampai pensiun tak punya rumah sendiri, sebab ayah lebih suka menyekolahkan engkau dan tiga orang adikmu sampai selesai SMTA? Nah selamat bertugas. Doa-ku menyertaimu dirantau”
Memang, kadang aku agak meragukan keampuhan petuah mantan guru itu. Kupikir itu kan zaman ayah dulu? Sedang sekarang kan zaman pembangunan? Masak iya nasib guru tidak berubah? Tapi sebagai anak yang taat, aku tetap menggenggam erat petuah itu dan menjadikannya sebagai suluh dalam melangkah menuju masa depan.
2
Yang pasti, sekarang ini di rantau orang sedikit banyaknya aku mulai merasakan betapa sulitya menjalani kehidupan sebagai seorang guru SD. Aku yang masih berstatus bujangan, belum punya buntut, toh setiap memasuki tanggal-tua pasti kalangkabut cari pinjaman, hanya untuk membeli gula kopi, rokok dan ikan asin. Beruntunglah aku mewaisi darah pendidik, hingga sampai hari ini aku masih senang menikmati sapaan: “Selamat pagi, pak guru!”
Godaan yang acapkali muncul sejak hari pertama bertugas adalah ulah segelintir orang yang sama sekali tak ada hubungannya dengan dunia pendidikan, namun silih berganti datang kekantor sekolah hanya untuk menjajakan barang-barang konsumtif. Mulai dari kosmetik, batik, perabotan rumahtangga sampai pada tivi, kulkas, sepeda motor dan macam-macam lagi ditawarkan oleh mereka.
Sudah penghasilan cekak, masih juga diiming-imingi barang kreditan. Repot memang. Mau menghindar cukup sulit, karena barang-barang itu terhidang didepan mata, lengkap dengan bahasa dagang yang manis dan merayu. Pada awalnya dewan guru termasuk aku memang sungkan, tapi lambat laun kami mulai terpengaruh juga ketika terpikir oleh kami betapa tidak mungkinnya kantong kami membeli secara kontan.
“Ambil saja, Pak….kan bisa dicicil selama sepuluh bulan. Murah kok, tidak berbeda dengan harga kontan dipasar.” Kalimat model begini paling sering berdendang di kuping kami, setelah berjam-jam sebelunya hanya mendengar celoteh para murid di kelas masing-masing. Rupanya paa guru itu dimata tukang kredit adalah sasaran empuk. Apa mereka kira gaji guru Impres itu jutaan? Atau di angapnya para guru punya penghasilan lain selain gaji; atau bisa mengkomersilkan jabatan? Huh!
Pada akhirnya hampir semua rekan guru disekolahku ini punya sangkutan hutang. Tak seorang pun yang terima gaji bulat, karena nyaris habis dipotong hutang. Mulai dari angsuran hutang di Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti yag dialami Ibu Kepsek dan pak Boce. Ada juga yang dipotong cicilan kredit motor, sehingga gajinya cuma bersisa lima ribu perak seperti yang dialami Ibu Maryatun. Lain halnya yang dialami oleh Ibu Maryani yang tinggal dikompleks, separuh gajinya terpaksa disetorkan ke tukang kredit perabotan rumah tangganya. Hal yang sama juga dialami oleh pak Lukman, Pak Isa, Ibu Rita, Ibu Ida………….pendeknya di setiap tanggal tua saban bulannya para guru pasti kalangkabut akibat defisit dalam neraca pembayarannya. Akan tetapi hidup ini memang aneh, karena tak selamanya dapat dijabarkan dengan fakta dan data. Betapapun kerontangnya isi kantong para guru, kok ya mereka semua bisa dengan selamat hidup dari bulan ke bulan? Rasanya para ahli ekonomi pemegang Hadiah Nobel sekalipun akan kehabisan teori untuk menganalisanya.
3
Sampai dengan tahun kemarin-alhamdulillah aku memang lolos dari terkaman tukang kredit. Toh akhirnya gajiku habis terbuang ke lobang WC dan hanya sebagian kecil saja yang sempat kutukarkan dengan karcis bioskop atau beberapa potong sandang. Jangan tanya dulu soal kirim wesel ke kampung, ayah tentu maklum.
Kupikir buat apa sepeda motor? Toh tempat kost-ku bisa ditempuh dengan jalan kaki. Perabotan rumah? Aku masih bujangan alhasil aku masih bisa menahan diri untuk tak tercebur dalam budaya kredit yang kian menggila.
Sayang ketabahanku itu berakhir di suatu siang dengan kemunculan pak Salim, seorang makelar tanah.
“Kapling itu berukuran 15x20 meter dua kilometer dari sekolah dan sampai saat ini sudah 60% di ambil peminatnya. Sisanya masih 10 kapling lagi, apa bapak berminat?” bola mataku mungkin bersinar, petuah ayah kini kembali mengiang di daun telingaku…..”Jangan turut jejak ayah yang sampai pensiun tak punya rumah, untung kakekmu ada meninggalkan warisan, coba kalau tidak ada?………….”
“Murah kok Cuma Rp 300 ribu tiap bulan, selama dua tahun”, tutur Pak Salim seolah bisa membaca isi hatiku.
“Tiga ratus ribu?”
“Benar” sambutnya cepat, “begitu pembayaran lunas, surat keterangan tanah berikut akte-nya langsung bisa bapak terima”
“Ambil saja pak Helmi. Hem….kalau saja gaji saya tidak sedang dipotong bank, tentu saya tak pikir dua kali,” dukung Pak Isa.
“Iya, saya juga begitu. Kan uang kita itu tak hilang percuma? Hitung-hitung buat investasi masa depan,” sambung Ibu Ida pula.
“Mumpung masih bujangan ambil kredit itu! Coba nanti kalau sudah punya buntut malah payah, Pak” timpal bu Maryani tak mau kalah.
Akibat petuah ayah ditambah dukungan rekan-rekan dan menariknya bahasa dagang Pak Salim, seminggu kemudian aku menyatakan persetujuanku. Lokasi cikal-bakal tanah milikku segera ku tinjau dan ku tandai dengan patok, disaksikan beberapa calon pemilik tanah lainnya.
Ahai, mulai bulan depan seperdua gajiku sudah ku investasikan demi rumah masa depan. Surat kilat segera kulayagkan ke kampung, “…………….Ayah berkat petuahmu, kini ananda mulai mencicil kredit kaplingan tanah…..Yakinlah, yah bahwa ananda takkan mungkin mengikuti jejak ayah. Ananda pasti punya rumah dan akan menyekolahkan cucu-cucu ayah kelak sampai universitas…….”
4
Memasuki tahun kedua, ketika angsuran ketiga-belas, akan kubayar aku memperoleh surat Panggilan dari Pak Lurah Keteguhan, desa tempat lokasi tanah itu berada. Di balai desa sudah berkumpul belasan orang lainnya yang beberapa diantaranya ku kenal sebagai calon pemilik tanah kaplingan. Semula aku beranggapan mugkin aku diundang dalam rangka rapat LKMD atau bisa juga upaya untuk mensukseskan program kerja Paket A atau…………….
Denga suara datar, akhirnya pak Lurah mengumumkan agar semua calon pemilik tanah Kaplingan dari pak Salim menghentikan pembayaran cicilan kredit tanah itu, sebab tanah itu telah disita Bank setelah pak Salim tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Sementara pak Salim pun kin masih dalam pencarian pihak berwajib ………………..
“Tobaaaaat…………..? Cuma itu yang keluar dari mulutku. Keringat dingin mengucur deras dari segenap pori-poriku, sedang pandangan mataku nanar dan dadaku berdebar tak keruan……………(Sukamaju, 2006)
DOKTORANDA
Cerpen asaroeddin malik zulqornain
Orang tua mana yang tidak merasa bahagia, bila mereka berhasil mendidik putra-putrinya telah meraih titel keserjanaan, sebab hal ini akan menaikkan prestise seseorang dan keluarganya ke tingkat yang lebih terhormat dimata masyarakat. Titel kesarjanaan merupakan modal buat memperolah pekerjaan yang layak.
Tapi ternyata gelar keserjaan bukan jaminan untuk membuat hidup bahagia. Hal ini dialami oleh Pak dan Bu mandok. Lima tahun lalu barangkali merekalah orang tua yang merasa berbahagia ketika mengetahui putri sulungnya telah berhasil meraih gelar keserjanaan, sehingga di depan nama anaknya itu berhak diberi tambahan title ‘Dra’.
Tapi sekarang, kabanggan yang mereka miliki nyaris pudar. Bertukar dengan kecemasan mengingat putri sulung mereka telah menginjak usia tiga puluhan namun belum menunjukkan tanda-tanda akan berumah tangga. Kecemasan mereka kian menjadi-jadi setelah Laras dan Larasati harus melangkahi Lastri, kakak mereka.. Lastri yang berpandangan modern biasa berfikir realasitis, tidak kecil hati untuk dilangkahi adik-adiknya. Sebalikanya Pak dan Bu mandok masih meyakini hal-hal yang irasional, kian cemas memikirkan nasib putri sulungnya.
Kecemasaan mereka memang beralasan kuat. Putri sulungnya itu memiliki persaratan yang lebih dari cukup untuk memikat perjaka yang bagaimanpun macamnya. Latri tergolong cantik, bertitel dan telah berkerja sebagai Kepala Bagian disuatu instansi. Dan di setiap malam minggu selalu saja kedatangan pria utntuk mengajak lastri berkencan. Sayang semuanya tak ada yang langgeng berhubungan. Mereka rata-rata datang pertama untuk yang terakhir.
Latri memang menerima dengan kedatangan terbuka setiap pria yang datang bertamu. Tapi tak gampang bagi Lastri untuk angsung tertarik pada Pria yang mengencaninya apalagi untuk nenjadikannya sebagai calon suami. Lastri terlampau selektif dalam memilih pasangan bahkan tetrkesan .terlampau berhati-hati. Ia terlampau tinggi menghargai sesuatu yang disandangnya! Lastri cendrerung berkaca pada dirinya sendiri sehingga tak satu pun pria yang cocok dimatanya!.
Malam ini diruang tamu nampak Pak dan Ibu mandok terlibat pembicaraan dengan putri sulungnya. Sebagai orang tua yang menginginkan anaknya bahagia. Bagai manapun perjodohan memang menjadi tanggung jawab mereka. Tugas mereka baru berakhir dalam mengawasi putrinya segera setelah Lastri berumah tangga.
“Anakku !.”kata pak mandok mengawali pembicaraaan sambil menghisap cerutunya dalam-dalam
“Ya, Ayah?!”sahut lastri sopan.
“Seminggu lagi bukankah engkau akan merayakan ulang tahunmu yang ketiga puluh nak?”..
2
“Benar, Ayah?!” tukas lastri sopan, .”tapi saya tidak punya niat untuk merayakan nya seperti tahun yang sudah-sudah”. lanjutnya kemudian
“Kenapa, nak!” tanya ibunya heran.
“Tak ada gunanya!”. Hanya menghambur-hamburkan uang,Bu!”
“Wah bisa-bisa pacarmu marah, nak!”. Pancing pak Mandok
“Pacar? Huh”.gumam lastri sinis.
“Jadi kau belum punya pacar tetap diantara teman-temanmu yang sering datang kemari itu, nak?!”
Lastri mengangguk, “Semua tidak ada yang cocok!”
“Jangan terlampau memilih, ingat usiamu, nak!” pinta ibunya sungguh-sungguh. “Kedua adikmu sudah punya anak, tinggal lagi dirimu, sampai kapan ibu harus bersabar, nak?!”
“Jodoh itu kan ditangan Tuhan, Bu?!”kilah Lastri
“Benar tapi jodoh itu tak akan datang dari langit jika kita tidak berusaha ke arah itu,”ujar Pak Mandok
“Lastri bukannya tak berusaha ayah”, timpal Lastri muram, ”Sayang semuanya belum ada satu pun yang cocok!”
“Bagaimana kira-kira calon suami yang kau dambakan itu, Lastri ?!”tanya ayahnya pura-pura tak tahu.
“Saya menginginkan calon suami minimal setaraf dengan status Lastri, Ayah” jawabnya mantap.
“kau menginginkan calon suamimu itu seorang sarjana?”Sela ibunya
lastri mengangguk mantap.
“Dan tak satupun diantara pria yang datang kemari itu seorang serjana?”tanya pak Mandok, .kembali lastri mengangguk.
Pak Mandok dan istrinya saling bertukar pandang, lalu menatap wajah anaknya dengan pandangan iba “Prinsipmu itu memang bagus namun jangan terlampau teguh memegangnya”.nasehat sang ibu sungguh-sungguh
Ia sengaja membunuh naluri kewanitaanya terhadap pria yang bukan sarjana. Lastri terperangkap oleh status yang disandangnya. Dia hanya memiliki kebahagiaan semu. Gelar keserjanaaannya merupakan duri dalam daging bagi gerak langkahnya!.
“Kau telah tidak jujur pada dirimu sendiri”, Ucap Pak Mandok dengan suara berwibawa, “Ingat, lastri! Tak ada gunanya segala macam titiel yang kau sandang itu jika pada akhirnya hanya menjerumuskan engkau pada kebahagiaan semu..Bagaimanapun telah tiba saatnya bagimu untuk mengkeranjang-sampahkan prinsip celaka itu. . Laki-laki sarjana bukan jaminan akan bisa jauh lebih baik ketimbang yang bukan sarjana, ia juga
3
bukan jaminanan bisa membahagiakanmu lahir dan batin, sebab kebahagiaan itu pada hakikatnya bukan datang dari luar tapi dalam dirimu sendiri, sadarlah kau sebelum terlanjur!”.
Lastri tercengung mendengar petuah ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Sungguhpun begitu bukan berarti Lastri mencairkan perinsipnya, Justrru kebenaran yang diucapkan ayahnya itu menambah keyakinannya. Lastri tetap kepala batu dalam soal ini.
“Lastri mengerti, ayah” Sambut Lastri, ”tapi janganlah Lastri terlampau di desak untuk segera berumah tangga, sebab Lastri tak ingin salah pilih yang pada akhirnya hanya akan mengecewakan hati ayah ibu”.
“ Lantas Sampai kapan kami harus bersabar?” Tanmya ibunya kemudian
“Sampai tahun depan ,bu!”
“Bagaimana jika sampai waktu itu juga kau belum juga menentukan pilihan hati mu?”
Baru lastri akan mencairkan prinsip, dan menyerahkan perjodohan ke tangan ayah ibu!”
Meski dengan perasaan berat, Pak dan Ibu Mandok mau tak mau mesti menyetujui usul putri sulungnya. Pak Mandok tak ingin turun tangan secara langsung karena sadar bahwa putrinya bukan perempuan kebanyakan. Tapi pula Pak mandok maklum kalau urusan perkawinan sepenuhnya ada ditangan putri sulungnya. Sebagai orang tuan ia cuma ‘Tut Wuri handayani’ dan berdoa setiap saat..
Tiga bulan kemudian kecemasan yang menghantui jiwa Pak dan Ibu Mandok mulai mereda ketika putri sulungnya itu untuk pertama kalinya memperkenalkan seorang pria kepada mereka.
“Ayah Ibu ini dokter Irwan, teman Lastri,”ujar lastri penuh ceria.
Tentu saja hal ini disambut dengan penuh kebahagiaan di hati mereka berdua.
Mereka berdua berdoa setiap saat agar hubungan putri sulungnya dengan dokter Irwan dapat terus berlanjut hingga kepelaminan. Doa mereka memang hampir terkabulkan ketika melihat putrinya sejak hari itu akrab dengan dokter Irwan. .Latri telah merintis kearah hidup berumah tangga dengan dokter Irwan, dengan meolak setiap laki-laki lain yang ingin bertamu kerumahnya. Agaknya Lastri telah jatuh cinta dengan laki-laki ini. Hubungan mereka kian lama-kian akrab. Dan Pak Mandok nyaris yakin jika pria yang satu ini memang cikal bakal jodoh anaknya. Nampaknya hubungan mereka tinggal mengunggu harinya saja untuk memasuki jenjang rumah tangga.
Hari yang didambakan oleh suami istri itu akhirnya tiba juga, ketika secara resmi dokter irwan malamar doktoranda Lastri. Pak dan Ibu mandok tentu saja menerima lamaran ini, “meski dokter Irwan malamar seorang diri tanpa disertai orang tua atau familinya. Kata dokter Irwan ayah ibunya telah tiada.
4
Pesta pernikahan segera dilangasungkan dengan meriah. Tak ada Orang yang lebih berbahagia setelah Lastri selain Ayah Ibunya, karena ini berarti tugas mereka untuk menjaga dan membesarkan darah dagingnya telah selesai.
Seminggu kemudian, sekembalinya pasangan yang berbahagia itu dari bulan madu. Rumah pak Mandok didatangai oleh tiga orang laki-laki tak dikenal bermaksud menjumpai anak mantunya dokter Irwan.
Dokter Irwan pada pagi itu kebetulan tidak sedang keluar kota ,seperti biasanya maklum masih pengantin baru. Ia segera menjumpai ketiga tamunya dengan wajah melambarkan kecurigaan. Ia mnyalami ketiga tmunya dengan tangan gemetar. Karena ketiga tamunya itu sama sekali tidak dikenalnya.
“Ada keperluan apa saudara-saudara ini?” tanya dokter Irwan dengan hati berdebar sementara Pak dan Bu Mandok serta Lastri mengikuti pertemuan ini dari ruang tengah yang cuma disekat dengan kain gorden
“Kami dari kepolisian”,ujar salah seorang diantaranya.
“Oo, jadi ketiga bapak ini adalah polisi? ada persoalan apa?”
“Pak Irwan!” Ujar salah seorang polisi itu berwibawa
“Kami mendapat perintah untuk menangkap bapak!”
Seketika wajah dokter Irwan berubah pucat-pasi.“Haah???apa kesalahan saya??Apa???
“Berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh dari laporan masyarakat. Anda ternyata seorang dokter gadungan!”.
Dari ruang tengah, terdengan teriakan histeris Doktoranda Lastri, sebelum akhirnya ia pingsan (Telukbetung, 1985).
TANAMAN MAKAN PAGAR
Cerpen asaroeddin malik zulqornain
Bedebah! Kini giliran sepatu dinasku yang belepotan tanah merah gara gara semalam aku malas memasukkannya ke dalam rumah. Malam Jum,at lalu giliran ayam jago bangkok-ku yang digondolnysa. Sebelum itu daster istriku yang sedang di jemur di suatu siang bolong; Lantas beberapa malam lalu, tiga buah ban becakku telah dicopot dari as-nya. Huh! Jangan jangan maling keperat itu tambah keblinger lantas nekad mencongkel kaca nako ruang tamu untuk menyapu bersih benda benda berharga yang ada dalam rumah.
“Pak, ada tamu!” suara istriku dari ruang tamu membuyarkan kegeramanku.
“Sebentar” bergegas kulangkahkan kaki menuju ruang tamu. Bola mataku kontan mendelik dan alis mataku pun mencuat begitu kutahu siapa gerangan tamu yang datang”Hmm….ini namanya ular cari pementung” desisku dalam hati sambil menatap tajam ke arah Hansip Markidun – tangan kanan Pak Erteku-, “Kamu mau nagih uang ronda, ya?!” tanyaku sinis
“Begitulah, Pak?!”
“Tiap malam kalian meronda itu buat haga keamanan kampung atau merondai geribikkamar, kalau saja ada yang bolong buat diintip?
“Wah, tentu saja yang pertama dong,Pak?!” jawab Markidun heran, “Memangnya kenapa, Pak?!”
“Kenapa? Apa kamu tidak tau kalau dalam tempo setengah bulan ini rumahku sudah empat kali kemalingan?”
Markidun Cuma melongo
“Sekarang begini saja” lanjutku penuh kejengkelan, ‘Sampaikan pada Pak Erte, bahwa Pak Asaroeddin baru mau bayar uang ronda jika maling itu berhasil dibekuk batang lehernya!”
Markidun kontan menggelinding dari depan hidungku tanpa ba bi bu, barangkali saja ia ngeri lihat podakku yang beringas ini
“Gop! Togop?!” teriakku ke arah dalam, memanggil pembantuku
“Ya, pak?!…bentar?!”
“Dia sedang ngisi bak mandi” tukas istriku
“Togoooooop?!
Togop kontan menghadap dengan tergopoh gopoh
“Dengar! Mulai besok kamu alih tugas jadi kelelawar saja” ujarku bernada perintah. Togop tentu saja bengong
“Kelelawar?!” cetusnya tanpa sadar
“Iyaa..Dari jam enam pagi sampai jam enam sore kamu boleh bebas tugas, tapi dari jam enam sore sampai jam enam pagi kamu harus melek terus, jadi centeng buat nangkap itu maling!” Tanpa pikir panjang, Togop langsung saja menyatakan kesanggupannya
“Bagus! Nanti kamu saya belikan golok dan lampu senter 6 batu. Kalau kamu berhasil membekuk itu maling, bakal saya kasih Bonus seratus ribu, oke?!”
“Tapi hari ini kamu masih tetap mengerjakan tugas-tugasmu yang biasa, Gop?!” sela istriku
“Saya, Bu” Togop pun langsung menggelinding ke belakang
Pagi ini kuputuskan tidak masuk kerja. Disamping tak punya sepatu dinas cadangan, pikiranku pun sedang uring-uringan. Aku memilih shoping ke Pasar Bambu Kuning buat beli sepatu dinas yang baru, perlengkapan centeng sekalian membeli tiga ban becak, biar Mukidi bisa menghidupi anak bininya kembali. Tapi berhubung sedang tanggal tua, terpaksalah aku ke Bank BNI buat cairkan ATM istriku.
“Lantas siapa nantinya yang akan ngurusi ayam-ayam dan ngisi bak mandi, pak” tanya istriku sedikit cemas
“Soal Ayam, ya tetap si Togop” tukasku mantap, “Urusan bak mandi biar nanti kusuruh si Kohar?!”
“Wah, bakal makan hati, Pak?!”sambut istriku, “Dia pasti ogah-ogahan mengerjakannya?!”
“Dulu bisa saja begitu, tapi sekarang tidak bisa lagi!” sanggahku,
“Dia sekarang sudah gede, sekolahnya saja sudah kelas tiga SMA. Sudah waktunya dia berbakti pada orang tua. Aku akan tindak tegas jika dia tidak mau kerja!”.
Begitulah. Seharian ini aku mengkosentrasikan diri untuk melakukan perubahan perubahan dalam rumah-tanggaku. Putra sulungku mau mengisi bak mandi. Mukidi kembali mengkomersialkan becakku buat cari setoran 500 rupiah sehari. Dan Togop telah mempersiapkan dirinya untuk begadang malam nanti dengan tidur siang sejak jam satu.
Malamnya menjelang tidur, istriku sempat melaporkan hasil kepergiannya sore tadi. “Aku sesungguhnya tidak pergi arisan, pak”.
“Haa? Jadi kau pergi kemana, Bu?.
“Kerumah Wak dukun Sampot”.
“Lha buat apa?. Kau kan tahu kalau aku tak percaya pada hal-hal yang irasional?”.
Tanpa mempedulikan sanggahanku , istriku langsung saja melapor, “Kata Wak dukun: maling itu orang dalam sendiri, Pak?”.
“Dan kau mempercayai ramalan edan ini?” tukasku jengkel.
“Engkau sendiri bagaimana?” tugasku balik bertanya.
“Tidak percaya!” jawabku tegas, “Masak aku mesti mencurigai dirimu, anakku, si Togop, Mukidi dan ayam kita, Bu?”.
“Tapi siapa tahu, Pak?”.
“ Buang ke laut pikiran konyol itu dari benakmu, Bu” pintaku setengah marah, “Maling itu jelas orang luar. Orang sekitar kampung kita ini. Kan sekarang ini sedang musim paceklik?” Istriku terdiam. Tidak menidakkan, tidak juga mengiyakan. Alhasil malam ini aku bisa tidur nyenyak, meski tengah malam tadi aku terpaksa
bangun untuk membukakan pintu rumah buat putra sulungku yang baru pulang dari main gitar di ujung gang, lagunya anak muda jaman sekarang.
“Mulai besok malam, kamu tidak boleh pulang ke lewat malam lagi, Kohar”, kataku padanya tadi pagi sebelum berangkat kekantor. “Pikirkan pelajaran-pelajaranmu, sebentar lagi kamu mau ujian”. Kohar mengganggukan kepala dengan perasaan berat. Ia memang sangat segan denganku, tapi dengan ibunya? Wuah, manjanya keterlaluan! Aku sering kali terlibat pertengkaran dengan istriku hanya gara-gara si Kohar.
Kini berkat adanya Togop semalam-malaman di depan rumah, maling itu enggan menampakkan batang-hidungnya lagi. Tapi di malam ke sepuluh, maling itu kembali bereaksi!.
Anggrek berikut pot-nya yang ditaruh istriku di halaman rumah yang digondolnya. Tentu saja Togop jadi sasaran kemarahanku.
“Lha wong maling itu lebih lihai dari saya, Pak” ujar Togop coba membela diri.
“Iya. Nanti giliran kepalamu itu yang akan digondolnya karena kamu keenakan molor, tahu?”.
Hh! Punah sudah ketentraman di hatiku. Meski rumahku sudah dicentengi, bukan jaminan bisa aman. Haruskan aku mempercayai ramalan Wak Dukun tempohari?. Bah! Tak mungkin! Sudah 15 tahun Togop mendarma baktikan tenaganya untukku. Kejujuran dan kesetiaanya tak perlu ku ragukan. Lantas siapa? Kohar-kah? Atau Mukidi? Atau istriku sendiri? Atau? Edan!.
Seminggu kemudian, ketika mataku hendak memicing, pintu rumahku digedor orang dari luar. Dengan bersungut-sungut aku keluar kamar.
Kuduga pasti yang di luar adalah si Kohar. Untuk itu aku sudah mempersiapkan kepalan tanganku. Bukan alang kepalang terperanjatnya aku begitu pintu terkuak!. Sebab yang berdiri di muka pintu bukan putra sulungku tapi 2 orang alat negara!. Dan pemberitahuaan yang keluar dari salah seorang di antaranya sangat mengejutkan.
“Putra bapak kini berada ditangan kami. Dia tertangkap basah bersama dengan dua orang temannya ketika sedang membongkar kandang ayam milik Pak Lurah Mukti!”.
“Kohar?”.
“Dia ikut-ikutan jadi maling demi untuk membeli minuman keras dan rokok ganja!”.
Langit serasa terbalik dan menghimpitlku. Putra sulungku telah melumuri mukaku dengan tahi ayam!. Tanaman yang kujaga dan kubesarkan dengan rejeki halal pada akhirnya memakan pagarnya sendiri! Tobat!.
Ulah putra bapak dan teman-temannya bukan lagi sekedar kenakalan remaja tapi sudah menjurus ke arah tindakan kriminalitas yang meresahkan masyarakat!”.
“Duh gusti….!”.
(Di muat pertama kali di Hr. SUARA KARYA MINGGU Edisi 6 Juni 1982)
(Kedua oleh Lampung Post Minggu Edisi 22 Januari 2006)
JAKARTA BUKAN SORGA
Cerpen Asaroeddin Malik Zulqornain
Sejak Bu Lasmi berprofesi sebagai ‘manol’, Dua tahun silam; Telah puluhan perawan desa yang berhasil ‘dijakarta-kannya’. Dia begitu gairah untuk turba ke desa-desa, khusus untuk menjajakan kehebatan kota Jakarta pada tiap perawan desa yang dijumpainya.
“Aku ingin membebaskan perawan desa dari belenggu kemiskinan dan kebodohan” demikian yang selalu dikatakan pada tiap orang, “Dan kota Jakarta selalu siap untuk menganugerahkan sejuta kenikmatan asal saja kita mau mendatanginya. Sebab cari kerja di sana terlalu mudah, seperti membalik telapak tangan, namun imbalan yang bakal kita terima, hmm….sangat menggiurkan”. Upayanya memang tak sia-sia. Terbukti tiap bulannya, Bu Lasmi pasti berhasil men-jakarta-kan empat sampai tujuh perawan desa sekaligus.
Tugasnya segera berakhir setelah hasil garapannya diserahkan pada nyonya besarnya. Tentang akan diapakan perawan desa itu oleh nyonya besarnya, Bu Lasmi tak ambil peduli. Bu Lasmi cuma tahu tiap satu kepala perawan desa akan dihargai lima ratus ribu rupiah oleh nyonya besarnya.
Banyak diantara perawan desa yang telah berhasil dengan aman di-jakarta-kan olehnya, tak lagi kedapatan pulang mudik. Mereka seolah-olah tenggelam dalam hiruk-pikuk belantara Jakarta penuh pesona, namun tak kalah angkernya dibanding alas roban Kalimantan.
Tapi bukan namanya seorang manol profesional jika Bu Lasmi tak lihai bersilat lidah dalam menentramkan hati para orang tua yang kehilangan anaknya, “Percayalah, anakmu kini hidup senang disana. Anakmu baru akan pulang setelah mengumpulkan uang yang cukup banyak”, demikian yang selalu diucapkannya pada orang tua yang menanyakan nasib anak gadisnya.
Berkat kerja kerasnya, kini Bu Lasmi berhasil merombak bangunan rumahnya yang dulu beratap rumbia, berlantai tanah dan berdinding bilik, jadi bangunan permanen, paling bagus nomor dua setelah rumah pak lurahnya.
Pun berhasil menukar perabotan rumahnya yang dulu serba kuno dengan yang serba luks. Dan orang yang paling beruntung menikmati semua ini tentu saja Pak Sastro, suaminya dan Dewi, putri semata wayangnya. Bahkan Dewi kini tumbuh jadi bunga desa Kuripan yang kaya tanpa harus di-jakarta-kan dulu oleh ibunya. Sejauh ini tak pernah terpecik niatan dalam kalbu Bu Lasmi untuk men-jakarta-kan putrinya, meski Dewi telah terlalu sering mengutarakannya.
“Kata ibu”, tukas Dewi suatu waktu setelah Bu Lasmi menampik keinginannya, “Jakarta itu kota sejuta kenikmatan, tapi kenapa anakmu sendiri tak kau perkenankan untuk mencicipinya?”.
“Itu semua cuma omong kosong, Dewi” –uff- hampir saja kalimat ini meluncur lepas dari kerongkongan Bu Lasmi, hal yang membuat Bu Lasmi harus kebingungan untuk beberapa saat, “Duh, Dewi telah termakan kata-kataku sendiri?” gumam Bu Lasmi dalam hati.
“Kenapa, bu ?’ desak Dewi penasaran.
“Sebab disana kau mesti bekerja keras dulu, Nak?!” , tutur Bu Lasmi sekenanya, “Untuk itu cukup ibu saja…”
“Tapi bu….” Potong Dewi cepat, :Mestikah anakmu ini sampai tua cuma jadi gadis dusun, sedangkan teman-temanku telah ibu jakartakan semuanya.”
“Jika engkau ke Jakarta, siapa yang akan merawat ayahmu dan rumah ini ?”.
“Huu… ibu hanya menginginkan aku jadi gadis dusun yang kuno dan bodoh. Ibu tidak adil…” teriak Dewi sambil berlari ke dalam kamarnya.
Sesungguhnya, ingin sekali Bu Lasmi menjelaskan pada Dewi kalau Jakarta itu bukan sorga. Ucapan-ucapannya selama ini cuma untuk menunjang profesinya belaka, cuma sekedar alat penjerat, cuma sekedar kata-kata. Sayang, pesan nyonya besarnya : “Sekali kau buka rahasia sebenarnya pada siapapun juga, tak peduli apa pada suamimu atau anakmu, berarti profesimu terancam, begitu pula keselamatanmu, Lasmi”, telah memperboden lidahnya.
Lain halnya bagi Dewi, justru semua cerita burung ibunya dipercayainya seratus persen. Kata-kata ibunya telah jadi bumerang dan membulatkan tekad Dewi untuk bisa ke Jakarta dengan cara apapun.“Jika gadis desa lainnya bisa, kenapa aku tidak ?. persetan dengan larangan ibu. Aku bukan gadis pingitan!”.
Jalan menuju Jakarta akhirnya terbuka lebar ketika dua orang gadis desa Kuripan yang telah dijakartakan Bu Lasmi, setengah bulan lalu pulang mudik. Siti dan Aminah – yang juga teman Lasmi – pulang dengan mengenakan pakaian yang serba indah, perhiasan emas puluhan gram, make-up yang menawan dan tingkah polah yang kebarat-baratan. Hal yang membuat Dewi iri dan sangat ingin seperti mereka. Segera Dewi mengutarakan keinginannya pada Siti dan Minah.
“Haa? Engkau ingin ikut kami ke Jakarta, Dewi?” sambut keduanya agak terperanjat.
Dewi mengangguk mantap, “Habis ibuku tak mau mengejakku!”.
Mendengar ini nampak Siti dan Minah tersenyum penuh arti.
“Memang Jakarta kota sejuta kenikmatan, seperti yang digembar-gemborkan ibumu itu, Dewi”, tutur Minah sinis, “Namun kenikmatan itu mesti kita tebus dengan harga yang sangat mahal. Dan kami berdua berkat upaya ibumu telah terlanjur menikmatinya.”
“Asal saja kau mau berjanji untuk tidak menyesal dikemudian hari dan takkan menyalahkan kami serta mau taat pada perintah kami berdua, “timpal Siti dengan suara tegar penuh kesan kegetiran yang mendalam, “Kami berdua siap untuk membantumu masuk Jakarta.”
Tanpa berpikir dua kali Dewi langsung saja menyetujui syarat-syarat yang dianjurkan sahabatnya. Nampak Siti dan Minah saling tukar pandang penuh arti kemudian tersenyum sinis.
“Aku yakin, “sambut Minah ”Modal yang kamu miliki cukup mampu untuk mengeduk uang sebanyak-banyaknya.”
Dewi sama sekali tak mengerti tentang makna kalimat-kalimat aneh yang dilontarkan oleh kedua orang calon “manol”nya ini. Dewi memang gadis desa yang masih polos yang terlanjur tertangkap oleh kata-kata ibunya sendiri. Perawan desa Kuripan yang jatuh cinta pada Jakarta!. Dewi sama sekali tak tahu kalau Minah dan Siti telah jadi korban kebejatan moral penghuni Jakarta. Bagi Minah dan Siti, kini justru terbuka peluang untuk membalaskan sakit hati mereka pada orang yang dulu telah menjual kehormatan mereka. Bagi Dewi, justru matanya bersinar-sinar bak gadis yang tengah kasmaran,
“Hmm… hampir tiba saatnya aku menghuni Jakarta yang dari pesawat tivi dan cerita ibu sangat menabjukan!” desis Dewi penuh luapan bahagia…
xxx
MALAM ini, di atas bis malam yang berlari kencang menuju metropolitan Jakarta, nampak duduk seorang wanita separuh baya pada bangku nomor lima kanan dengan wajah murung dan pikiran rancu. Berkali-kali ia bergumam luruh sambil mendesiskan sebuah nama, “Dewi… Duh, Dewi…!”.
Bu Lasmi malam ini mendatangi Jakarta tidak untuk menggembalakan perawan desa ke padang kebejatan moral, tapi untuk melacak sekaligus menjemput putri tungglnya yang kemarin malam telah pergi tanpa pamit dari rumah diajak oleh dua orang temannya yang sudah berpengalaman jadi penghuni Jakarta. “Gusti, lindungilah darah dagingku dari musibah,” gumam lirih Bu Lasmi yang kesekian kali. Dia baru ingat pada Tuhannya, meminta pertolongan Tuhannya ketika di pelupuk matanya membayangkan sebuah bencana yang akan menimpa putri tunggalnya. Perasaan Bu Lasmi kini jauh lebih parah ketimbang perasaan para orang tua perawan desa yang telah dijakartakannya.sebab Bu Lasmi, tahu apa yang akan dialami para perawan desa itu setibanya di Jakarta. Bu Lasmi merasa bus yang ditumpanginya ini berlari terlalu lambat, dia ingin bus ini berlari sekencang-kencangnya. Sama sekali Bu Lasmi tak sadar kalau bus yang ditumpanginya ini telah dilarikan supirnya dengan kecepatan maksimum yang membahayakan keselamatan jiwa penumpangnya.
Tiba-tiba saja rasa berdosa menguasai jiwa Bu Lasmi. Di pelupuk matanya kini bermain-main puluhan wajah para gadis desa yang telah dirumuskannya ke lembah duka, dan wajah para orang tua si gadis yang merindukan anak gadisnya yang hilang ditelan belantara Jakarta. Tiap wajah itu selalu tersenyum sinis dan menuding dirinya. Bu Lasmi tak kuasa mengakui sepak terjangnya selama ini. Jiwanya sangat tersiksa dan rasa penyesalan yang dalam kini berkharisma dalam jiwanya. “Gusti, maafkanlah dosa-dosaku, maafkanlah.selamatkanlah putriku dari bencana, lindungilah ia…” gumam lirih Bu Lasmi dengan mata berkaca-kaca, “Aku bertobat, Gusti!” pekiknya dalam hati, ”Aku akan berhenti jadi manol bila putriku berhasil kau kembalikan padaku, Gusti!. Tolong, tolonglah, Gusti…”Sementara bus kian menggila kecepatannya, sang supir kian dalam menekan pedal gasnya, menerjang kegelapan dengan kecepatan tinggi, seolah pinta Bu Lasmi dikabulkan Tuhan.
“Karma?” cetus Bu Lasmi tanpa sadar, “Karma??” gumamnya kian jelas terdengar membuat beberapa penumpang di dekatnya menoleh kepadanya. “Tidak, tidaaaaaaaaaak!” pekik Bu Lasmi tanpa sadar dengan keringat dingin yang bercucuran. Pekik ini begitu keras sehingga mampu tertangkap oleh telinga sang supir, membuat konsentrasi sang supir buyar dan sejenak menoleh kearah datangnya teriakan.
Pada ketika itulah mobil yang dilarikan dengan kecepatan tinggi harus mengalami kefatalan!.Roda-rodanya keluar dari aspal, menabrak pagar pengaman disebelah kanan jalan dan langsung terjun kejurang yang menganga lebar! “Toloooooooooongnngng..”teriakan histeris berkumandang menembus gulita malam untuk menyambut datangnya malaikat maut!.
Persis pada detik itu pula, Dewi tengah berjuang mempertahankan kehormatannya dari renggutan paksa seorang lelaki hidung belang Jakarta di sebuah kamar hotel berbintang lima, “Tidak! Tidaaaaakk!” teriak Dewi dengan pakaian yang koyak moyak, “Ibuuuuuu!”.
Dan lelaki itu Kian beringas, “Hahahaha……….
PELURU TERAKHIR
Cerpen Asaroeddin Malik Zulqornain
LELAKI PERKASA BERGELANG AKAR BAHAR itu telah menghabiskan lebih dari separuh usianya untuk bertualang. Dia memang seorang lelaki tualang sejati yang tak pernah kenal kata menyerah untuk mewujudkan setiap ambisinya. Tiap batu kegagalan yang ditelannya tak pernah membuatnya jera apa lagi patah semangat. Justru sebaliknya kegagalan itu dijadikannya sebagai cemeti, perangsang untuk melucut semangatnya kian menggebu-gebu lagi. Dia tak pernah menunggu peluang tapi secara sengaja dan sadar menciptakan peluang. Waktu tak mampu meninabobokannya. Dia nyaris berjaya mengangkangi waktu. Dan yang lebih penting lagi, dia selalu bekerja seorang diri. Segenap hamba-hamba hukum di Republik ini mengenal sepak terjangnya. Di setiap baku saku hamba-hamba hukum ada tersimpan potret dirinya. Semua mereka menjadikan dirinya sebagai binatang buruan. Kepalanya telah dihargakan 1 juta dollar. Namanya telah menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang berpangkat dan berduit. Tapi bagi rakyat kecil dia justru jadi “pahlawam tak dikenal”. Dia adalah si belut, si kancil, si bandit ulung yang dicari-cari. Dia juga satu-satunya sahabat karibku.
SAHABATKU bertualang tidak untuk memperkaya dirinya, tidak untuk main perempuan, mabuk-mabukan, apalagi main judi. Semua hasil kerja kerasnya yang bertentangan dengan hukum bernegara dan hukum Tuhan justru telah habis dibagi-bagikannya kepada orang-orang papa. Dia berkejahatan untuk mencari kepuasan batin. Dia baru bisa bahagia apabila uang hasil merampok bank telah dibagi-bagikan ke panti-panti asuhan anak yatim, wisma-wisma orang jompo dan ke yayasan sosial lainnya. Dan dia akan tertawa terbahak-bahak ketika membaca koran yang memuat sepak terjangnya. Sebegitu jauh dia tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pahlawan orang miskin. Dia merampok, membunuh orang-orang berduit tidak untuk membela si lemah. Dia bekerja untuk dirinya. Dia ingin menjadi pahlawan bagi dirinya!.
Malam ini selepas isya, dia kembali mendatangi rumahku. Kini berdiri tegak didepanku, membuka topeng yang menyelubungi wajah aslinya. Tapi malam ini ia tak membawa serta uang hasil operasi (padahal ia sudah sebulan tak datang). Lazimnya setelah ia menggondol uang hasil kejahatannya ia langsung menyetorkannya padaku untuk kubagi-bagikan ke yayasan sosial di segenap penjuru tanah air via pos wesel.
“Kedatanganku malam ini barangkali untuk terakhir kalinya, Mandok”Cetusnya membuka pembicaraan, datar tanpa nada.
“Terakhir?” Desisku heran. ia mengangguk lemah.
Kubesarkan nyala lampu minyak yang ada di atas meja ingin kubaca ekspressi wajahnya lebih jelas lagi.
“Apakah aku tak salah dengar> Ia menggeleng.
“Apakah aku tengah bermimpi?
“Juga tidak!” sergahnya sediit keras.
“Dengar, Mandok” Lanjutnya dingin, “Malam ini aku memutuskan untuk terakhir kalinya kita bertemu!”.
“Kau akan meninggalkan aku?”
:Begitulah….”
“Kau akan pergi ke mana?”.
“Aku tak tahu.”
“Apakah kaupun akan berhenti merampok?”.
“Ya!”
Aku menghela napas dalam-dalam. Perubahan ini terjadi begitu tiba-tiba, sukar kuterima dengan pikiran normal.
“Kau telah insaf dan ingin bertobat?”
“Tidak!” Sanggahnya mantap.
“Karena apa yang kulakukan selama ini selaras dengan keyakinan yang ku anut.”
Aku tercenung dengan pikiran rancu, sulit menduga semuanya yang sebenarnya.
“Malam ini kita harus berpisah!” Tukasnya kemudian dengan nada dingin dan tekanan yang dalam.
“Yeaaaah…. aku tak keberatan jika memang sudah menjadi keputusanmu, bahkan aku bersyukur….
Tiba-tiba ia mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya; pistol berlaras ganda. Menggenggamnya, membuka kuncinya, “Sobat…
“Hmmm.”
“Peluru pistol ini tinggal sebutir lagi…”
…….????
“Aku berniat untuk menghadiahkan peluru terakhir ini pada dirimu!”. Cetusnya kemudian tanpa nada sambil mengarahkan moncong pistol ketangannya ke keningku.
“Kau ingin membunuhku?”
Ia mengangguk lemah.
Srr….tersirap darahku, tergetar seluruh tubuhku. Pada akhirnya apa yang selama ini menjadi ganjalan dalam benakku mendekati kenyataan, aku akan disingkirkan setelah dianggapnya aku tak dibutuhkan lagi. Ini memang hukum dalam dunia kejahatan. Aku menghela napas dalam-dalam jiwaku tiba-tiba saja kembali menjadi tenang untuk menerima kenyataan pahit ini!.
“Lakukanlah! Ujarku tegas dan mantap.”
“Apa yang akan kau lakukan ini sudah sejak lama ku duga.”
“Bagus!”
“Tapi bolehkah aku pada detik terakhir untuk mengetahui penyebab utama kau membunuhku?”
Kini ia yang menghela napas dalam-dalam. Wajahnya berubah muram, “Aku telah jatuh cinta sobat?!” Tuturnya lemah nyaris tak terdengar.
Aku tersenyum sinis. Pada akhhirnya lelaki perkasa yang tak pernah mengenal rasa cinta, terbakar juga akhirnya oleh api asmara.
“Siapakah gerangan perempuan yang kau cintai itu?”
Di luar dugaan, ia justru menggeleng dan tersenyum kecut, “Aku tidak pernah mencintai perempuan lain selain almarhum ibuku.” Timpalnya tegas.
“Lantas kepada siapa kau jatuh cintanya?”.
“Tak satupun manusia di dunia ini yang ku cintai?”
“Ya, tapi bukan kepada manusia, justru kepada kematian!” Tuturnya membuat aku tercengang.
“Kematian dessisku tanpa sadar.
“Sobat aku berkeinginan ecepatnya bercumbu dengan maut, aku mendambakan kedamaian yang abadi!”.
“Tapi kenapa peluru yang terakhir itu justru akan kau kirim kejidatku, bukan kejidatmu? Apakah ucapanmu barusan Cuma igauan seorang penjahat licik? .
Kembali ia tersenyum penuh miseri, memasukkan tangan kirinya ke saku jaket kulitnya. Sejurus kemudian tanggan kiri itu telah menggenggam seutas tali pelastik.
“Aku akan mengakhiri hidupku lewat tali pelastik.” Ujarnya sambil merentangkan tali pelastik di tangannya, “Ini akan kulakukan sehabis kukirim peluru terakhir ini ke jidatmu.”
“Hoo kau ingin mati lewat menggantungkan diri?”
Ia menangguk lemah.
“Ingin ku rasa bagaimana sakitnya saat meregang, bercumbu dengan sang maut!”
“Apa yang akan kau lakuakan jelas menunjukan kekerdilan dirimu sekaligus kepengecutan dirimu, sobat!” Tuturku dengan nada mengejek.
“Tapi inilah jalan terbaik bagiku untuk meniadakan hidup yang tidak menghidupi ini.” Timbalnya cepat.
“Aku sudah jenuh dengan kebahagian semu yang selam ini ku kenyam. Aku telah tertipu. Aku tak memperoleh apa-apa dari seluruh sepak terjangku selain rasa cemas dan ketakutan untuk Ditangkap. Sesungguhnya aku telah mendera nuraniku terus-menerus!”.
“Jadi keyakinan yang selama ini mendarah daging dalam dirimu itu merupakan kebahagian semu?”.
“Ya, sebab sampai detik ini aku belum menemukan hakekat diriku yang sebenarnya. Semua yang telah kulakukan Cuma kujadikan sebagai media mencari idetitas diri. Tapi hasilnya nihil! Aku tak pernah mengenal diriku dengan baik!”.
“Kelak kau akan mati penasaran. Rohmu akan bergentayangan. Kedamaian abadi pasti akan jauh dari arwahmu.Berpikirlah realitis, bersikaplah jantan, seperti yang selama ini kau lakukan. Kenapa kau mesti berpaling dari kejantanan?”.
“Aku sudah muak dengan semua itu. Muak dengan diriku. Aku telah membenci diriku sendiri!”.
“Ingat sobat!” Ujarku bersungguh-sungguh.Perjuangan mencari identitas diri itu memang tak pernah mengenal kata akhir. Setiap orang akan menemui batu kegagalan bila mengarahkan dirinya kesana. Sesungguhnya hidup dan kehidupan ini misteri abadi. Kita Cuma tahu melakoninya tanpa tahu arah yang mesti kita tempuh. Siapapun di dunia ini tak pernah berhasil menemukan identitas dirinya. Tentang itu Cuma relatif. Visi diri kita akan terus berkembang selaras dengan acuan waktu. Waktulah yang telah berjaya atas diri manuasia, bukan sebaliknya. Kegagalan mencari identitas adalah hal yang lumrah sebab jika semua orang mengenal dirinya dengan baik, dunia ini tak perlu memiliki polisi, penjara, hakim dan jaksa, sebab semuanya akan berjalan serasi dengan hati nurani manusia. Dan kau pun tahu kalau nurani manusia itu suci dari kejahatan bukan?”.
Beberapa jenak ia tercenung, barangkali mencoba memamah kata-kataku barusan.“Tapi aku harus mati, desisnya dengan suara tergetar, “Engkaupun demikian!”.
“Setiap makhluk bernyawa akan mati. Mati adalah suatu akhir kehidupan yang akan datang dengan sendirinya, sesuai dengan kehendakNya tak perlu dipaksa datang!:
“Kenapa tidak sekarang saja kita berdua mati?” cetusnya datar sambil menatapku dingin, “Bukankah makin cepat makin baik?”.
“Jika kau ingin membunuhku, itu memang wajar, karena ini berarti Tuhan telah membua nyawaku lewat tangan mu, bukan karena kehendakku. Tapi jika kau ingin bunuh diri pakai tali pelastik, hah inilah cara yang dimurkaiNya. Alam pasti tak bakal menerima arwahmu, sobat! Kau akan mati penasaran Karena cara itu adalah pertanda kepengecutan menghadapi resiko hidup!.
Sampot, sahabat karibku membelalakan matanya lebar-lebar, lalu tertunduk, pistol ditangannya pun jatuh ke lantai berbarengan dengan kejatuhan dirinya mencium lantai. Sebutir peluru yang dilepaskan oleh oknum penegak hukum yang berdiri di belakangnya telah bersemayan persis di jantungnya!.
(Dimuat Majalah Detektif & Romantika (D&R) Edisi 0837 Tanggal 15 Maret 1982 Halaman 52 sd 54)
**********
TURUN MALAM
Cerpen asaroeddin malik zulqornain
Di jelang pagi manis bangkit dari baringnya nun dari balik perbukitan hijau yang menelikung kota: Bukit Wan Abdurrahman; Sepasang Merpati tua, Tamong Mandok dan Minan Itun turun dari rumah panggungnya di Pekon Lempasing yang berpantai pada ceruk teluk laut penuh plankton yang bila malam tiba seakan bintang gemintang turun dari langit malam, menaburi kawasan teluk Lampung bagai kunang-kunang, itulah geliat para pencalang laut sejati yang tengah asik memperdaya ikan-ikan dengan menebar jala, mata kail, lampu petromak dan doa-doa. Sebagai pencalang laut sejati, seperti halnya Mandok di laut mereka berjaya tapi di darat mereka senantiasa diperdaya oleh para tengkulak. Sungguhpun demikian, mereka tetap setia menarikan tarian hidupnya sebagai kunang-kunang Teluk Lampung!
Akan halnya sang istri, Minan Itun akan berpisah dengan sang suami, bergabung dengan ayunan puluhan pasang kaki telanjang lainnya menerabas jalan setapak yang masih berembun dengan menating pelita bambu sambil punggung menggendong atawa bahu memikul hasil huma masing-masing untuk melakoni peran Turun Malam. Kelak di pasar-pasar tradisional para petani dan pencalang itu akan bersinergi ‘menyuapi’ warga se kota yang masih lelap di buai mimpi. Sunguh suatu kota yang menjanjikan berjuta pesona!
Pesona kota itulah yang barangkali membius tiga orang putra mereka : Pipin, Pitut dan Pido untuk merantau kenegri impian, sungkan mengikuti jejak mereka, sungguhpun di kota besar, mereka cuma hidup sebagai karyawan kecil bergaji pas-pasan, dan hal inilah yang membuat sepasang merpati tua itu merasa kesepian di hari tuanya.
2
“ Mereka sudah mulai melupakan kita, Bang........” cetus Minan Itun Lirih di jelang Minggu Petang lalu ketika dipastikan salah seorang dari putranya itu tidak ada yang datang mengunjungi mereka.
“ Ya sudah...” sambut Tamong Mandok sambil menghembuskan asap rokoknya, “Mungkin mereka sibuk dengan urusan keluarga masing-masing” lanjutnya datar
“ Tapi mereka kan anak kita? “ sambut istrinya cepat, “Tidak bisakah mereka menyenangkan kita? Meluangkan waktunya untuk menjenguk kita? Sebagai tanda bakti seorang anak? Khan kita tidak minta apa-apa dari mereka, kita Cuma minta mereka dengan anak dan istrinya datang, itu saja kok tidak bisa?” lanjut Minan Itun kelu. Tamong Mandok enggan menjawab, karena bedug maghrib telah bergema, turun dari rumah panggung untuk sholat berjamaah di masjid.
Pipin, Pitut dan Pido dipastikan akan pulang kampung jika mereka membutuhkan tambahan biaya hidup di kota. Sebagai orang tua, sudah barang tentu tidak ingin hidup anaknya susah. Beragam alasan yang harus mereka telan, Mulai dari sewa rumah, biaya mantu melahirkan, sampai ke biaya cucu sekolah Sepertinya sudah menjadi garis tangan kehidupan sang pencalang dan istrinya untuk terus berpendar sebagai matahari yang hanya wajib memberi tapi tak patut menerima. Sungguhpun sebagian harta dan tenaga mereka sudah habis terjual untuk biaya sekolah dan pernikahan ketiga putranya. Untuk itu mereka harus terus hidup berhemat, karena yang kini tersisa cuma Rumah Panggung, perahu kecil, sebidang huma dan empat pasang tangan keriput dimakan usia. Yang penting bagi keduanya setia dan ikhlas menjalani peran sebagai sang pencalang laut dan bidadari turun malam sampai maut menjelang!
3
Membesarkan titipan tuhan dengan rezki halal dari air bergaram dan kehijauan, sepatutnya hari tua mereka menjanjikan, atau setidaknya menikmati buah yang telah mereka semai dari kerja keras berpuluh tahun lewat bakti dari ketiga putranya, seperti yang sering mereka saksikan dari beberapa tetangga di Pekon Lempasing. Sayang garis tangan keduanya beda dengan beberapa tetangganya, mereka berdua tetap abadi sebagai sang pencalang tua dan bidadari tua turun malam. Sisa sisa tenaga tua mereka terus memintal hari esok dengan terengah-engah dan sama sekali tak terpikirkan untuk purna bakti dari dinginnya gelinjang gulita berembun dan cekaman air bergaram!
Semula pernah keduanya berangan, bahwa ketiga putranya itu setelah kost bertahun-tahun untuk menuntut ilmu di kota. Setelah tammat, bisa kerja sebagai pe-en-es atau polisi, beristri cantik, punya mobil, tiap minggu datang menjenguk, sukur-sukur dinaikkan haji. Sayang hal seperti itu cuma igau. Ketiganya memang telah berhasil tammat sekolah, kerja swasta., beristri, tapi cuma hidup pas-pasan rumahpun masih ngontrak nun di kota besar sana! Angannya jauh panggang dari api.
“ Kita berdua tak sekolah, nyatanya bisa menghidupi anak kita ya bang?” cetus Minan suatu waktu,
“ Karena kita kerja keras sebagai nelayan dan petani ” sambut suaminya
“Coba kalau mereka bertiga pulang kampung saja, kerja seperti kita, tentu mereka tak perlu susah mikir biaya kontrak rumah, dan pasti mereka bisa hidup, karena kita masih punya laut dan gunung, khan bang?”
Tamong Mandok tersenyum, “Tapi mereka sungkan hidup sebagai orang kampung. Maunya jadi orang kota terus. Mau apa lagi?” sambutnya dengan nada getir
4
Sang Bidadari renta itu tetap turun malam, menggendong hasil humanya dan terkadang bersua dengan sang suami: sipencalang laut renta di pasar tradisionil, guna menyuapi warga kota dengan ikan dan sayuran justru ketika warga kota masih lelap di buai mimpi, hasilnya sebagian ditabung untuk menyuapi ketiga putranya suatu waktu. Lagu hidup ini terus mengalun merdu dalam daur ulang hidup dan kehidupan sepasang merpati tua itu.
Nampaknya sang waktu tak selalu seirama dengan ayunan langkah sepasang merpati tua itu. Salah satunya harus digerus waktu dan izrail lebih suka memilih sang pencalang laut sejati: Tamong Mandok! Peristiwa itu terjadi sebulan lalu, kini Sang Bidadari Renta harus menjalani takdirnya sendiri di medan waktu entah sampai kapan!
Minan Itun bertekad tetap turun malam sebagai bidadari renta yang menyuapi warga kota, seperti halnya di malam ke empat puluh berpulangnya sang pencalang, sungguhpun ketiga anaknya bermalam di rumah panggungnya guna membahas hari tuanya.
Ketika gulita menggigil di selimuti embun, sang Bidadari bersijingkat turun dari rumah panggungnya, menuai laku turun malam, melewati ketiga tubuh putranya yang pulas di buai mimpi, dia tidak berjalan tapi terbang dengan Jung milik sang pencalang. Perahu itu dipenuhi beragam hasil huma yang serba hijau. Terbang membelah langit malam dengan setia. Di bawahnya berpendar perahu nelayan bermandikan cahaya petromak guna memperdaya ikan-ikan Teluk Lampung,
“Bang...” Gumamnya kelu, “Izinkan aku tetap mensuplai warga kota dengan sayuran dari huma kita” lanjutnya, “Aku ingin tetap berhuma, ingin tetap berbagi kehijauan dengan warga kota, sungguhpun ketiga putramu sepertinya akan menghalangiku dengan segala cara. Tapi aku tetap ingin berumah panggung, tetap berhuma, tetap ada di dekatmu....” Perahu itu kini terbang memasuki kawasan perkotaan,. Satu persatu rumah tinggal anaknya disinggahi. Dilihat mantu dan cucunya berdesakan dalam tiga rumah kontrakan di tiga sudut kota yang kumuh dan sempit.
5
“Bagaimana mungkin aku akan hidup di kota, Bang?” Gumamnya perih, “Ketiga putramu pun hidup berdesakan di perumahan kumuh. Aku disuruh tinggal di rumah mereka. Berhenti menyuapi warga kota, dan cuma menyuapi cucu-cucuku saja. Sepertinya tak mungkin, bang...” rintihnya sambil terus berputar-putar di kawasan perkotaan sambil membagi-bagikan sayuran hijau ke segenap warga kota dengan gratis, “Aku takkan mungkin mau menuruti permintaan ketiga putramu itu, bang..” rintihnya sambil kembali ke Pekonnya di Lempasing. “ Aku bagaimanapun juga tak ingin berpisah dari engkau dan rumah kita, bang!”
Dan ketika pagi manis bangkit dari balik Laut Teluk Lampung, saat ketiga putranya meminta kepastian Minan Itun untuk memenuhi permintaan mereka. Dengan nada pasti, sang Bidadari renta Turun malam itu bertutur, “Bunda tetap Turun Malam dan Berhuma”
“Bunda sudah tua, sudah saatnya beristirahat” Ujar Pipin
“Bunda mesti hidup di kota” Tambah Pido
“Bunda sekarang sakit-sakitan dan tak ada yang memperhatikan” Timpal Pitut
“Terima kasih, putra-putraku. Jadilah anak yang berbakti. Biarkanlah Jung, huma dan rumah panggung ini tetap jadi milik Bunda, toh tak lama lagi Bunda akan menyusul Bapak kalian, setelah itu baru kalian bebas untuk berbuat apapun termasuk menjualnya, tapi tidak sekarang”
“Bunda?????” (Sukamaju, 051108)
CERPEN : "TERPELANTING"
Sebagai Pamong, aku cuma bisa merekomendasikan Tarmi ke Kepala Pekon, sebagai Penerima BLT, Beras Raskin dan Kartu Jamkesmas. Hal itu terjadi setahun lalu, ketika perempuan Estewe, ibu Pipin, Pitut dan Pido yang masih kecil-kecil harus menghidupi keluarganya sendirian karena Sampot – suaminya- harus ‘sekolah’ di Elpe akibat menggarap Hutan Kawasan tanpa izin. Ihwal pinjam uang sejuta buat memenuhi permintaan petugas hutan jika ingin kasus suaminya tak diperpanjang sampai polisi, jelas tak bisa kubantu, darimana aku uang?
Akupun tak mampu menjawab ketika Tarmi dengan tersedu menuturkan kemalangan nasibnya, “Apa salah suami saya? Hutan ciptaan Allah. Kami menggarap tanah kosong yang ada dicelah-celah pohon raksasa dengan menyemai bibit pisang dan kopi itupun sudah berlangsung hampir sepuluh tahun lalu? Tak ada pohon yang kami tebang karena kami cuma punya golok dan cangkul. Kenapa ketika saat memetik hasil keja keras berhuma, lantas disalahkan? Kenapa tidak sejak awal kami membuka hutan langsung dilarang? Hu…Tolong saya, Pak?!”
Sialnya, aku bukan Robinhood yang dengan panahnya mampu datang ke penjara guna membebaskan kliennya. Parahnya pula ini bukan Jaman Robinhood, ini Jaman Duit jadi Raja dan Era Dukun Ramal masuk Tivi. Pembalak liar semacam Badar tentu tak punya modal buat nyogok. Dia cuma punya niat untuk menjadi seorang kepala keluarga yang bertangungjawab, walau untuk itu dia mesti kerja keras sendirian di hutan larangan, penuh dengan satwa liar, jerat dan bantingan dan akhirnya dia benar-benar terjerat dan terbanting! Masuk hotel predeo selama setahun melanggar pasal merusak hutan sebagai pembalak liar!
Coba kalau aku Juragan, tentu uang sejuta bukan soal, toh jika ikhlas memberi, tentu bermanfaat sebagai celengan akherat. Menurut hematku, sesungguhnya Sampot bukanlah Perusak hutan, justru dia turut menghijaukan hutan, menjaga keasrian hutan dengan tambahan tanaman yang bisa dipastikan tak bakal menyakiti pohon-pohon besar disekitarnya. Ah, kalau saja hutan kawasan itu berada dalam wilayah kekuasaanku, tentu akan kudatangi si petugas yang menangkap wargaku itu, kubebaskan dia disertai sumpah serapah kepada si Petugas. Sayang, hutan itu berada di Kabupaten-kecamatan dan Pekon yang lain! Tapi ini mungkin akal-akalan si Petugas, sebab kata Tarmi tadi, kenapa tidak sejak awal dilarang? Kenapa baru sekarang? Ah, jangan-jangan setelah melihat hasilnya, muncul ‘sirik’ si Petugas? Ya Bisa saja, tapi darimana duit sejuta?
2
Tarmi dan ketiga anaknya sudah tiga tahun jadi wargaku, numpang membangun rumah geribik beratap rumbia di tanah Tamong Kilah, seratus meter dari rumah tinggalku. “Karena tiga anak saya harus sekolah dan mengaji, maka saya turun gunung dan tinggal disini, Pak. kami tidak ingin nasib anak-anak kami seperti orang tuanya…” lanjutnya pula membuat hatiku kian terenyuh.
Dalam hati aku memuji Tarmi. Kemiskinan yang dia geluti sekarang kalau bisa jangan sampai diwarisi anak-anaknya kelak. Dan dia percaya, lewat sekolah dan mengaji paling tidak ketiga anaknya kelak bisa meraih hari depan gemilang! Tidak seperti mereka berdua, sejak kecil tidak mengenyam sekolah, sepakat kawin, masuk hutan kawasan sebagai penggarap Tanah Huma Liar. Hal ini dilakukan karena tanah warisan orang tuanya dinyatakan sebagai Tanah Register, alias Tanah Negara. Dan sebagai Rakyat yang tak tahu hukum, mereka terima nasib bahwa huma garapannya kini sekarang telah berpindah tangan secara otomatis sebagai Tanah Negara! Sampot dan Tarmi mau mengadu kepada siapa? Orang Tuanya telah tiada, Berperkara ke Pengadilan tak tahu caranya, kalaupun tahu darimana biayanya buat membayar pengacara?
“Ya Sudah…bersabarlah…..Mungkin Tuhan sedang menguji kalian” sambutku menghibur
“Tapi kenapa kami terus-terusan hidup dalam ujian Tuhan, Pak?”
“Bersabarlah…..” Ya cuma ucapan ini yang bisa saya utarakan untuk menguatkan keimanan Tarmi. Selebihnya terbentur aturan, karena sebagai Pamong, saya harus terus menerus menggembar-gemborkan slogan Pemerintah bahwa hutan adalah paru-paru dunia, hutan harus kita lestarikan Sungguhpun dihati kecil saya berteriak, “Kenapa manusia-manusia bercangkul seperti halnya Sampot dikategorikan Perusak Hutan? Mereka tidak punya modal, tidak punya buldoser, tidak punya kemampuan untuk merobohkan pohon-pohon raksasa, tapi kenapa mereka harus dihukum sementara yang jelas-jelas menikmati hasil hutan sebagai cukong dan taipan hidup ongkang-ongkang sebagai manusia terhormat, bahkan Adelin Lis mampu kabur dari Penjara hanya karena dia punya Duit!
“Kalau begitu Tuhan tidak adil, ya Pak?!”
“Hus…Istigghfar, Bu..” sambutku kelu, “Yakinlah suatu hari nanti derita ibu akan berakhir. Dan saya bersama warga kampong akan sebisa mungkin membantu ibu. Saya berjanji!
3
Walau semula dengan tergagap-gagap ketika menghidupi keluarganya, Tarmi sedikit demi sedikit mampu menyiasati peran sebagai orang tua tunggal. Manusia memang punya kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang dialaminya, sepanjang yang bersangkutan mau berusaha dan tidak mudah putus asa. Kini Tarmi paling tidak telah mandiri tanpa melacurkan diri sungguhpun untuk itu dia setiap hari harus berperan ganda, sebagai ibu dan Kepala Keluarga! Beragam kerja serabutan dilakoninya, mulai dari bangun pagi buta melakukan ngodok memunguti biji tangkil di kebun-kebun tetangga, berburu keong di celah-celah rerumputan seusai hujan reda, buruh pembuat emping melinjo, sampai mencari kerang di laut ketika air surut.
Kebetulan sekali wilayah tinggal kami diapit oleh pegunungan dan pantai. Bertani tangkil dan nelayan adalah pekerjaan bagian terbesar warga kampung. Hidup sederhana, saling tolong menolong sudah menjadi lagu hidup wargaku dan musibah yang dialami Tarmi dianggap musibah kami pula, maka selamatlah Tarmi dari hidup lintang pukang. Pekonku bukan tanah air mata tidak juga tanah bermata air, namun dengan kerja keras dan jalinan kekeluargaan yang tulus antar sesama warga, paling tidak mampu meyakinkan Tarmi bahwa dia pasti bisa berperan sebagai orang tua tunggal!
00000
Siang bermendung sebulan lalu, Tarmi, Pipin, Pitut dan Pido bersimbah air mata bahagia, karena ayah tercinta kembali dari penjara. Dan Tarmi pada saat itu terpikir untuk mengembalikan tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga kepada suami tercinta. Aku bersukur, karena sebagai Pamong aku berhasil menjaga kehormatan Tarmi dari kemungkinan jamahan pria hidung belang!
“Terima kasih, Pak” ucap Sampot di senja kembalinya dari penjara, “Bapak telah banyak menolong kami” lanjutnya dengan terbata-bata.
“ Berterima kasihlah pada Pemerintah dan tetangga” Sambutku sungguh-sungguh,
“Jadikan pengalamanmu sebagai guru bagi kehidupanmu di hari hari mendatang”
“Ya Pak. Akan saya usahakan” cetusnya pula dengan takzim.
“Kamu suami yang beruntung karena memiliki istri semacam Tarmi” ucapku kemudian membuat Tarmi tersipu-sipu
“Ya, Pak” ujarnya sambil mengerling pada istrinya
“Tapi, Pak?!” Cetus Tarmi
4
“Ada apa lagi, Tarmi: sambutku bertanya-tanya
“Suami saya ini minta izin untuk menjenguk humanya”
“Ah, buat apa lagi?” Sambutku khawatir, “Bukankah Pemerintah sudah melarangnya? Hilangkan impianmu menikmati buah kerja kerasmu dari berhuma kopi dan pisang itu, mungkin sekarang sudah ditebang, sudah jadi hutan kembali” tuiturku kemudian
“Paling tidak untuk melihatnya saja, Pak?!” Sambut Sampot memohon
“Tak usah, jangan cari penyakit” tukasku mantap
“Kalau sudah dihutankan kembali ya tidak apa-apa, Pak” tukasnya pula, “Tapi saya sakit hati jika Huma saya itu tetap ada dan hasilnya dinikmati oleh Petugas yang menangkap saya…”
“Lebih baik lupakan!”Perintahku tegas, “Kau, bisa saya pastikan akan kembali ditangkap mereka”
“Ya Pak!
“Bagus” sambutku lega. Karena jika pintanya kusetujui, bisa dipastikan ia akan berputih mata, sebab Huma itu tetap ada, hanya kini dikuasai oleh Penguasa Hutan Kawasan! Hal ini bukan dugaan, mata kepalaku sendiri yang menyaksikannya ketika berkesempatan mendatangi Huma-nya dua bulan lalu!
“Untuk sementara, Pakailah perahu milik saya” ucapku kemudian memecah kebisuan, “Cobalah jadi nelayan, mudah-mudahan cocok”: lanjutku kemudian
“Wah, saya lagi-lagi merepotkan Bapak?” sambutnya dengan tergagap
“Terima kasih, Pak” sambut istrinya pula
“Bagaimana? Bersedia?” Tanyaku kemudian
“Akan saya coba, Pak?!”
Sepanjang bukan masalah uang, Sebagai Pamong, saya memang harus membiasakan diri untuk membantu warga yang kesulitan. Seperti halnya Sampot, sebagai seorang mantan narapidana, dia harus mengembalikan kepercayaan dirinya yang hilang akibat hidup dibalik jeruji besi. Dia harus dikembalikan kepervcayaan dirinya sebagai Kepala Keluarga yang bertanggungjawab dengan berikhtiar lewat cara-cara yang halal .
Tak terasa sebulan sudah Sampot bergelut dengan gelombang dan perahu untuk memperdaya ikan-ikan dengan mata kailnya, hidup sebagai nelayan!
Sampai suatu pagi berhujan, Tarmi dengan sesunggukan kembali menghadapku
“Ada apa lagi Tarmi? Apa Kau dipukuli suamimu??”
Tarmi menggeleng
5
“Suamimu kawin lagi?
Tarmi menggeleng sambil menundukkan kepalanya dengan air matra kian bercucuran
“Kalau semua bukan, apa yang membuat kamu menangis sepagi ini?
“Anu, Pak
“Anu Apa?
“Semalam Bang Sampot ditangkap polisi!”
“Ditangkap????”Tukasku penuh keterkejutan, “Salah apa lagi suamimu?”
“Kata polisi, Bang Sampot di duga akan mencuri ikan kerapu dalam keramba milik Cukong Alay karena perahu Bang Sampot bersandar dekat pantai berkeramba milik mereka, Pak!?”
“Tuhan, betapa susahnya hidup jadi orang miskin di negri ini!” pekikku, “Jika hutan dan pantai ciptaanmu hanya boleh dinikmati oleh orang-orang berpunya dan berkuasa, lantas tempat dimana lagi kami boleh hidup menikmati ciptaanmu!”
(Sukamaju, 191108)
Diposkan oleh Mandok Lampung di 19:36
U M U R
Cerpen Asaroeddin Malik Zulqornain
Sore nanti jam lima, aku akan memperingati peristiwa keluarnya aku dari rahim ibu untuk kali yang kedua lima. Di sini, di kantor kelurahan, sebagai petugas, aku seperti biasanya datang lebih awal dari Pak Lurah. Duduk termangu di muka mesin tik tua membuat pikiranku terbang kepada peristiwa nanti sore dirumah.
Tak terasa aku kini sudah beranjak dewasa, pagi ini adalah pagi terakhir bagi usia ke dua puluh lima yang aku miliki. Hari terakhir untuk hidup yang kedua lima. Aku sepertinya dikejar perasaan gelisah yang tak ku tahu dari mana asalnya. Benar! Menghadapi detik-detik terakhir usia dua lima, bukannya aku bergembira seperti halnya tahun-tahun yang sudah, malah sebaliknya aku mesti merasa gelisah. Apakah ini gara-gara aku mendengarkan ceramah Kyai Martubi semalam yang bercerita tentang arti hidup, kematian dan hidup sesudah mati, barangkali juga. Entah sudah berapa kali yang keberapa dan mengusap-usap mukaku tanpa kutahu jelas apa sebabnya aku melakukan demikian.
Aku mencoba mengusir kegelisahanku tanpa sebab ini dan menggantinya dengan b\hal-hal yang menggembirakan. Terbayang dipelupuk mataku kalau ibu dan adikku Lina tengah mempersiapkan hidangan yang lezat untuk para tamu yang akan merestui kehadiranku di dunia ini. Terbayang olehku tentang Lisa pacarku. Entah kado apa yang akan dihadiahinya untukku, dan sebagainya dan sebagainya.
Tengah aku asik dilambungkan khayal acara nanti sore, tiba-tiba terdengar suara orang memanggil dari luar, “Assalamualaikum!”
“Waalaikum salam, langsung masuk saja” sambutku pada pak tua yang berdiri didepan pintu, Ia lalu melangkahkan kakinya mendekatiku, menyalamiku, “Pak lurah sudah datang, nak?” ucapnya kemudian sambil meletakkan pantatnya di kursi yang terletak di muka mejaku.
“Sebentar lagi datang. Bapak ingin ketemu beliau?”
“Begini nak? Berhubung Bapak akan menengok anak di Jakarta besok pagi, maka Bapak akan minta surat jalan
“Oo….. Berapa lama pak?” Ujarku sambil bangkit dari duduk pergi ke almari untuk mengambil blanko surat jalan.
“Kira-kira seminggu sampai dua minggu.
“Bapak punya KTP”
“Tidak, nak?
2
“Surat pengantar dari RT?
“juga tidak.
“Wah, Bapak ini benar-benar koboi, ya” selorohku.
“Habis saya tidak tahu, sih”
“Baiklah kita mulai saja. Nanti jika saya tanya, bapak langsung menjawab, ya?” ujarku sambil memasukkan blanko ke dalam rol mesin tik tua……..
“Iya, nak?
“Kita mulai sekarang………Nama Bapak?
“Parto”
“Umur?”
“ngng………….terserah anak saja.
“Lho kok terserah saya”
“Habis bapak tidak tahu persis”.
“Bapak tidak punya primbon kelahiran”.
“Tidak”.
“Kalau begitu coba bapak kira-kira sendiri”
“Maaf, nak. Bapak tidak bisa mengira-ngira.
“Dibiasakan dong. Masak umur sendiri tak tahu.”
“Sungguh nak, saya tidak tahu sama sekali sebab orang tua saya dulu tidak mencatatnya.
“Kok bisa begitu”.
“Tau”
“Bagaimana kalau saya tulis disini lima puluh?”
“Boleh”
“Enam puluh?”
“Pokoknya terserah anak mana yang kira-kira tepat, tulis saja. Saya tidak penting umur, saya penting surat itu.
Mendengar ucapan ini, aku benar-benar tersinggung. Dia secara tidak langsung telah menegurku. Pak tua ini menyepelekan tentang umur sedang aku malah sebaliknya, meributkannya, memperingatinya, menjadikannya sebagai batu peringatan untuk menghadapi hidup hari esok. Apakah aku yang salah atau dia yang salah? Entahlah. Yang pasti perasaanku kini terguncang mengingat sebentar lagi aku akan memperingati Hutku.
“Jadi bapak tak pernah berulang tahun?” Cetusku tanpa sengaja.
“Ulang tahun? Apa itu?
“Peringatan hari lahir”
“Oo kalau itu tidak pernah”
3
“Kalau beitu apa saja hari-hari yang berarti dan Bapak peringati selama hidup bapak.
“Paling juga memperigati arwah orang tua Bapak”
“Kapan itu”
“Setahun sekali”
“Nah itu bapak catat dan bapak anggap penting”.
Ya, tapi penting bukan untuk saya melainkan untuk almarhum agar arwahnya selamat dari api neraka.
“Justru orang yang masih hiduplah yang seharusnya memperingati hari kelahirannya. Karena dengan jalan ini, ia bisa mengoreksi sampai berapa jauh perjalanan hidup yang sudah ditempuhnya. Bapak tentu menyayangi hidup ini, bukan.
“Tentu dong nak”
“Dan Bapak kepengen panjang umur bukan?
“Ya sudah pasti”
“Kalau begitu jangan sia-siakan hari kelahiran Bapak, carilah dan tanyakan pada keluarga Bapak terdekat”
“Buat apa”
Buat apa?! Ya untuk tanda kita mencintai hidup ini.
“Bukan begitu caranya mencintai hidup ini nak. Sebab hidup bukan untuk diingat-ingat tapi untuk dijalani dengan penuh gairah sampai nanti datang panggilan untuk menghadap-Nya.
“Tapi tanggal kelahiran itu patut diketahui pak tua”
“Bagi bapak itu hanya akan mengingatkan bahwa lobang kubur akan semakin dekat kita jelang. Bertambah setahun selangkah jarak kita dengan lobang kubur!”
Mendengar ini kontan meremang bulu kudukku. Apa yang dikatakan pak tua ini benar adanya!
“Kalau begitu Bapak takut mati dong!” ujarku mencoba menutupi ketakutanku sendiri.
“Bapak bukannya takut mati, karena mati itu pasti akan kita temui, hanya saja Bapak tak ingin memikirkannya. Bapak ingin menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya sebelum ajal datang menjemput!
Entah kenapa tiba-tiba perasaan takut mati menghantui diriku, aku betul-beul dipengaruhi oleh ucapannya.
“Sudahlah nak, tuliskan sekehendak anak tentang umur Bapak”
“ Saya tidak sanggup, pak”
4
“Tuliskanlah nak” pintanya menghiba.
“Bapa saja yang menyebutnya”
“Saya tidak berani memastikannya atau mengira-ngiranya.
“Apalagi saya”
“Kalau begitu kosongkan saja”
“Huss mana bisa”
“Kasihanilah saya, nak”
Melihat raut wajahnya yang diselimuti mendung, akhirnya tak kuasa menahannya berlama-lama aku takut kalau dia berkata yang lebih seram lagi tentang umur yang nantinya bisa berakibat aku kehilangan gairah untuk memperingati ulang tahunku. Akhirnya
aku megambil kebijaksanaan : di kolom umur Cuma kutuliskan kata-kata TIDAK TAHU PERSIS!
Sepeninggal Pak tua aneh yang tidak mau tahu berapa umurnya itu, aku tecenung di muka mesin tik seperti halnya sebelum dia datang. Kali ini bukan memikirkan tentang ulang tahun nanti tapi tentang arti ulang tahun itu sendiri………..Dan ucapan Pak tua barusan sangat berkesan dijiwaku. Memang benar! Semakin bertambah usia kita semakin dekat lobang kubur kita jelang…………. Ah umur.
SORE HARINYA DIRUMAHKU ketika semua undangan sudah hadir dan acara ulang tahunku akan dimulai…………aku melakukan suatu perubahan yang cukup berarti: Kue ulang tahun yang diatasnya tersusun lilin dua puluh lima biji yang nanti nyalanya akan kupadamkan sebagai tanda berakhirnya usia dua lima, kini kutambah dengan sebatang lilin yang agak besar ditengah-tengahnya.
Dan tepat pukul lima sore aku tidak meniup lilin ulang tahun tapi sebaliknya:Menyalakan kedua puluh enam lilin itu!. (Sukamaju, 1980)